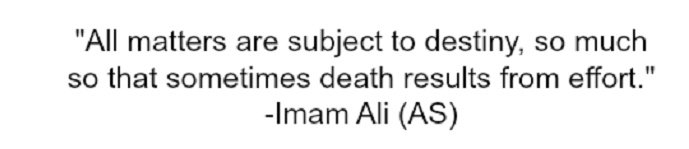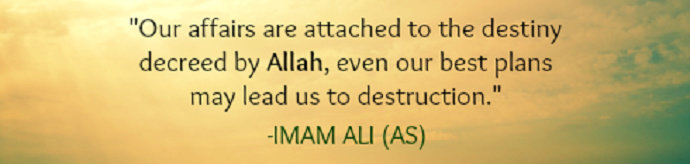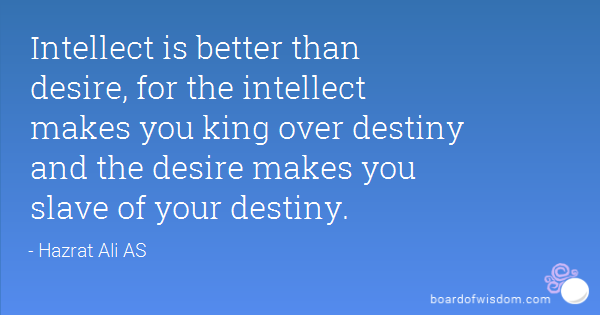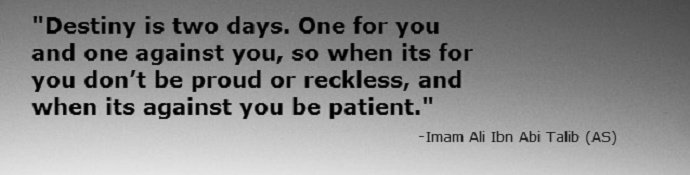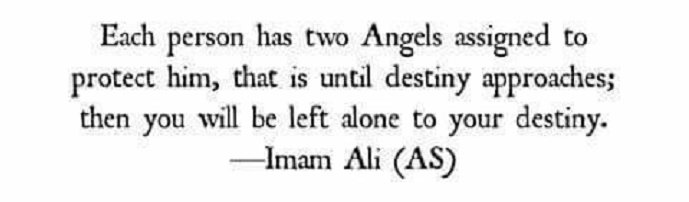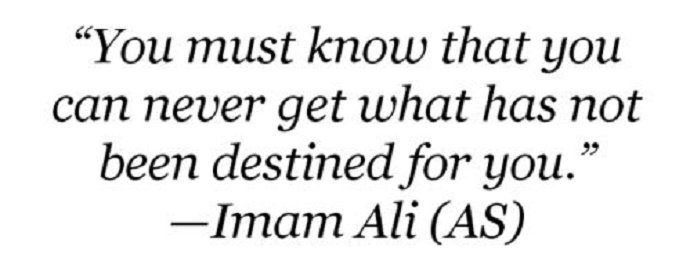Kata takdir diderivasi dari bahasa Arab qaddara yuqaddiru taqdîran, yang berarti menaksir atau mengira. Jika syiddah-nya dihilangkan maka menjadi qadara, yang berarti mampu. Dari sini dikenal salah satu sifat Tuhan yakni qudrah (Mahakuasa).
Dalam akidah Islam biasanya kata taqdir disandingkan dengan kata qadâ` dan lebih sering disebut qadâ dan qadar. Penggunaan kata takdir dalam pembahasan ini bukan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan yang lebih menitikberatkan kepada penggunaan atau apresiasi terhadapnya daripada pembahasan mengenai pengertian. Kata takdir digunakan dalam posisinya yang dianggap berlawanan dengan kebebasan kehendak (ikhtiar atau free will) dan apa yang dipahami oleh para teolog.
Arifin Jami‟an melihat ada tiga pengertian takdir dari segi etimologi:
-
Takdir merupakam ilmu yang amat luas meliputi segala apa yang akan terjadi dan semua yang berhubungan dengan itu. Semua hal yang akan terjadi pasti telah diketahui dan ditentukan sejak semula.
-
Takdir berarti sesuatu yang sudah dipastikan. Kepastian itu lahir dari penciptanya di mana eksistensinya sesuai dengan apa yang telah diketahui sebelumnya.
-
Takdir berarti menerbitkan, mengatur, dan menentukan sesuatu menurut batas-batasnya di mana akan sampai sesuatu kepadanya, sebagaimana tercermin dalam al-Quran surat Fushshilat ayat 10.
Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.
KH Taib Thahir setelah melihat penggunaan kata qadâ dalam al-Quran mengartikan qadâ` dengan hukum yang ditetapkan Tuhan sejak zaman azali mengenai segala apa yang akan terjadi. Qadar diartikan dengan merancang dan merencanakan sesuatu dengan perhitungan paling mendalam dan teliti. Juga mengetahui semua batas, hubungan, dan sebab akibat yang terjadi setelah perencanaan itu terwujud. Dengan demikian Taib melihat secara etimologi tidak terdapat perbedaan mendasar dalam keduanya. Dari sana keduanya disebut qadar atau takdir saja sebagaimana digunakan dalam hadis Nabi saw,
“Dan percaya kepada takdir, baik dan buruknya.”
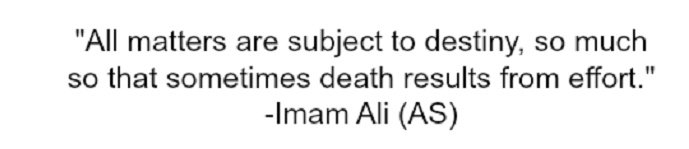
Dja‟far Amir mengartikan takdir dengan ketentuan-ketentuan yang mesti berlaku atas tiap-tiap makhluk, sesuai batas-batas yang telah ditentukan Tuhan sejak zaman azali, baik ketentuan yang baik maupun yang buruk, semua akan terjadi sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Sedangkan qadâ` berarti keputusan yang telah terjadi sesuai dengan ilmu serta takdir Tuhan sejak zaman azali.
M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa takdir terambil dari kata qaddara, berasal dari akar kata qadara yang antara lain berarti mengukur, memberi kadar atau ukuran. Dicontohkan jika dikatakan bahwa Allah telah menakdirkan demikian, maka berarti Allah telah memberi kadar, ukuran, atau batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya. Istilah takdir mirip dengan sunnatullah atau hukum alam, tetapi takdir setingkat di atasnya karena hukum-hukumnya tidak hanya terjadi pada alam, melainkan juga pada hukum-hukum kemasyarakatan.
M. Taqi Misbah Yazdi mengatakan bahwa kata qadar berarti ukuran (miqdar) dan takdir (taqdir) berarti ukuran sesuatu dan menjadikannya pada ukuran tertentu, atau menciptakan sesuatu dengan ukuran yang ditentukan. Sedangkan qadha` berarti memutuskan dan menuntaskan sesuatu, yang di dalamnya menyiratkan semacam unsur konvensi. Kedua kata ini terkadang digunakan secara sinonim yang berarti nasib.
Muthahhari, seorang ulama Syi‟ah, mengatakan bahwa qadâ berarti penetapan hukum, atau pemutusan dan penghakiman sesuatu. Seorang disebut qâdi karena tugasnya menghakimi dan memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa di pengadilan. Qadar berarti kadar dan ukuran sesuatu. Setiap kejadian alam jika ditinjau dari pengawasan dan kehendak Tuhan dapat dikelompokkan ke dalam qadâ` Ilahi dan jika dilihat dari sudut keterbatasan sifatnya pada ukuran dan kadar tertentu pada kedudukannya di dalam ruang dan waktu dapat dikelompokkan ke dalam qadar Ilahi.
Jamaluddin al-Afghani menolak ajaran qadâ dan qadar yang mengandung paham fatalistik. Ia berpendapat bahwa qadâ dan qadar mengandung arti bahwa segala sesuatu terjadi menurut sebab akibat. Kemauan manusia merupakan salah satu mata rantai hukum sebab akibat. Qadâ` dan qadar menurutnya sinonim dengan hukum dan ciptaan Tuhan.
Fazlur Rahman, sejalan dengan al-Afghani, menolak jika takdir disamakan dengan predeterminisme. Ia mengatakan bahwa sebenarnya perkataan qadar berarti memberikan ukuran atau keterhinggaan dan ide yang terkandung dalam doktrin qadar bawa Allah saja yang tak terhingga secara mutlak. Segala sesuatu selain-Nya sebagai ciptaan memiliki tanda ukuran dan keterhinggaan, dengan kata lain memiliki jumlah potensi yang terbatas—walaupun jangkauan potensi-potensi ini, seperti yang terdapat pada manusia kemungkinan sangat luas.
Berbagai pengertian mengenai takdir di atas terlihat terpecah kepada dua kutub besar sebagaimana digunakan pada penjelasan secara klasik. Takdir didefinisikan antara hukum atau pengetahuan Tuhan semenjak azali dan juga sebagai kadar atau ukuran segala sesuatu. Namun demikian sebelum definisi-definisi tersebut telah berlaku pendefinisian takdir yang lebih tua dan yang berasal dari aliran-aliran teologi dalam Islam, yakni Jabariah, Muktazilah, dan Ahlussunnah yang terbagi kepada Asy‟ariah dan Maturidiah.
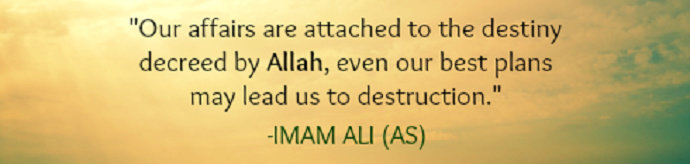
Seputar Takdir dalam Islam
Sejak zaman primitif manusia selalu menyertakan kepercayaan akan takdir bersamaan dengan kepercayaannya terhadap sembahannya. Takdir diilustrasikan sebagai kekuatan luar biasa yang menentukan kesenangan dan kekuasaan hidupnya. Takdir belum terbayangkan sebagai aturan yang telah ditetapkan untuk kelangsungan hidup alam semesta. Takdir dibicarakan baik oleh kaum Hindu, Babilonia, Mesir kuno, Yunani, Yahudi, Kristen, Islam, juga para filosof dari berbagai agama dan kebudayaan tersebut. Berbagai pendapat yang dilontarkan tidak terlepas dari dua paham ekstrim yang mengatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bahwa manusia terikat dalam genggaman takdir.
Pembicaraan takdir dalam Islam tidak terlepas juga dari pengaruh berbagai agama dan kebudayaan sebelumnya. Sebagaimana dalam tema lainnya, dalam hal ini pun para teolog maupun filosof Muslim sangat terpengaruh oleh pandangan para filosof Yunani. Plato mengatakan bahwa semua tuhan adalah baik dan dari tuhan- tuhan itu hanya akan lahir kebaikan. Kejahatan timbul akibat dari kurang-nya pengetahuan dan kebodohan. Manusia terjerumus ke dalam kejahatan karena kepadatan materi (hayûla) merintangi usaha untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Menurutnya segala sesuatu yang ada di alam wujud merupakan gambaran ideal yang ada di dalam akal tuhan. Kejahatan bukan berasal dari takdir tuhan. Kebebasan manusia menuju kesempurnaan tidak dibatasi oleh takdir tuhan, tetapi oleh rintangan materi yang amat padat itu (hayûla). Hayûla inilah yang merintangi manusia bagi terwujudnya kemampuan yang dikehendaki tuhan.
Pemikiran takdir menurut Aristoteles sejalan dengan pemikirannya dengan sifat Tuhan. Menurutnya, Tuhan sama sekali tidak mencampuri urusan alam dan semua yang ada di dalamnya, baik yang bernyawa maupun tidak. Karena itu Tuhan tidak menentukan urusan apapun juga bagi alam, sebab takdir tidak sesuai dengan kesempurnaan sifat kemutlakan Tuhan. Zat yang sempurna dan mutlak kesempurnaannya tidak membutuhkan apapun juga selain zat-Nya, tidak menghendaki sesuatu, dan tidak memikirkan sesuatu salain zat-Nya sendiri. Hubungan antara Tuhan dan alam tidak lebih dari sebagai penggerak pertama yang tidak bergerak. Sejalan dengan pemikirannya tersebut, Aristoteles menga-takan bahwa setiap manusia bebas memilih sesuatu bagi dirinya sendiri. Tidak ada qadâ‘ maupun qadar. Setidaknya manusia bisa menahan diri jika ia tidak bisa melakukan suatu perbuatan. Sedangkan tujuan bagi setiap makhluk hidup ialah mewujudkan sesuatu yang diperlukan oleh eksistensinya menurut cara yang sesuai dengan eksistensinya.
Ibrahim Madkour beranggapan mustahil jika problematika takdir dalam Islam telah berkobar pada masa awal perkembangan umat Islam. Problematika takdir mendapatkan porsi ketika fitnah yang menimpa khalifah Usman bin Affan di mana sesama umat Islam bersengketa antara yang mendukung tahkîm (perdamaian) dan yang menolak. Setelah itu mulai dipertanyakan tentang posisi orang yang melakukan dosa kecil dan besar, apakah masih termasuk mukmin, kafir, atau justru berada di antara keduanya. Madkour menyimpulkan bahwa problematika takdir dalam Islam terjadi pada paruh kedua dari abad pertama Hijrah.
Yahya al-Dimasyqi berpendapat bahwa perbuatan manusia ada dua macam, yakni terpaksa (jabariah) dan bebas memilih (ikhtiariah).
-
Jabariah ialah perbuatan yang terjadi tanpa terasa seperti pertumbuhan tubuh, dorongan karena pengaruh kebutuhan alami seperti makan, atau yang terjadi dikarenakan faktor kesalahan seperti anak panah yang diarahkan kepada binatang buruan tetapi (kebetulan) mengenai manusia.
-
Perbuatan-perbuatan ikhtiariah ialah perbuatan yang timbul dari kehendak manusia secara murni, setelah adanya pemikiran dalam rangka merealisir kelezatan atau manfaat. Perbuatan ikhtiariah ini merupakan perbuatan yang dibarengi dengan adanya kemampuan dan kehendak yang berada dalam jangkauan manusia untuk mengerjakan atau meninggalkannya.
Perbuatan jabariah merupakan perbuatan Tuhan, sedangkan perbuatan ikhtiariah adalah ciptaan manusia.
Ma‟bad al-Juhani ialah seorang tabi‘i dan ahli hadis yang tidak setuju dengan sikap penguasa yang melegitimasi kekuasaan mereka dengan paham takdir. Dalam sikapnya, ia mengingkari takdir yang bisa menegasikan kebebasan kehendak manusia. Sikap Ghailan al-Dimasyqi terhadap takdir sama seperti Ma‟bad, di sisi lain ia adalah orang kedua yang mengangkat problematika setelah Ma‟bad. Diantara butir pemikirannya ialah bahwa Allah tidak berbuat kecuali yang baik, perbuatan manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri, dan Allah tidak akan menyiksa hasil perbuatannya sendiri sedangkan Dia adalah Zat yang Mahaadil.
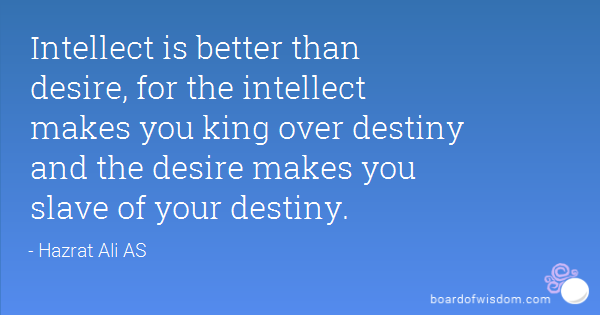
Jabariah
Sebagai “tandingan” paham Qadariah tersebut kemudian lahir paham Jabariah yang dipelopori oleh al-Ja‟d bin Dirham (abad VIII M) dan Jahm bin Safwan (m. 127 H/745 M). Paham ini mengatakan bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan dalam diri manusia. Manusia tidak memiliki kekuatan dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Menurut Jabariah manusia diibaratkan sebagai wayang yang tidak bergerak kecuali digerakkan oleh dalang. Bertolak belakang dengan Qadariah, menurut Jabariah manusia tidak memiliki kebebasan, semua perbuatannya telah ditentukan oleh Tuhan semenjak azal.
Jabariah memegang prinsip bahwa perbuatan manusia telah ditentukan semenjak zaman azali. Manusia tidak memiliki daya untuk melakukan sesuatu. “Segalanya berasal dari Tuhan.” Tuhan memiliki kekuatan absolut terhadap segala sesuatu, termasuk kehendak dan perbuatan manusia. Abdul Hye menyebut pandangan Jabariah ini dengan “pure fatalistic view".
Pada hakikatnya paham Jabariah menyakini bahwa bahwa semua perbuatan dan gerak-gerik manusia ialah perbuatan Allah yang dialirkan melalui hamba-Nya. Sehingga dengan keyakinan itu manusia tidak perlu usaha, ikhtiar, maupun inisiatif sama sekali.108 Meskipun demikian ada juga diantara kaum Jabariah yang berfikir moderat berpendapat bahwa perbuatan—sebagaimana adanya—terjadi karena kekuasaan Allah. Akan tetapi dalam hal taat dan durhaka, perbuatan itu terjadi atas kemauan manusia sendiri.
Qadariah
Paham Qadariah kebanyakan diwakili oleh para pemikir dari kaum Muktazilah. Muktazilah dipelopori oleh Wasil bin „Atha‟, seorang yang dikenal i‘tizâl (memisahkan diri) dari majlis al-Hasan al-Bashri karena ketidakcocokannya dengan gurunya mengenai posisi orang Mukmin yang mela-kukan dosa besar di akhirat nanti. Tidak puas dengan jawaban gurunya, Washil mengatakan, “Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya; tidak mukmin dan tidak pula kafir.”
Harun Nasution mengatakan bahwa diantara penyebab Wasil mendirikan paham Muktazilah ialah ketidaksetujuannya dengan kaum Khawarij maupun Murji‟ah mengenai masalah yang sama. Kaum Khawarij berpendapat bahwa orang Mukmin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Sedangkan kaum Murji‟ah yang muncul sebagai reaksi terhadap kaum Khawarij yang mengatakan bahwa orang Mukmin yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir, tetapi tetap Mukmin. Persoalan mengenai dosa besarnya diserahkan kepada Tuhan di akhirat nanti. Wasil mengatakan bahwa orang tersebut tidak mukmin dan tidak pula kafir, melainkan mengambil posisi diantara keduanya. Jika sebelum meninggal ia bertobat maka akan masuk surga dan jika sampai meninggal ia tidak sempat bertobat maka nasibnya akan sama dengan orang kafir dan tidak akan masuk surga. Paham ini dikenal dengan al- manzilatu bain al-manzilatain.
Muktazilah
Aliran Muktazilah memegang prinsip bahwa manusia memiliki kekuatan penuh untuk melakukan sesuatu dan memiliki kebebasan dalam memilih pilihannya. Meskipun demikian mereka tetap mengatakan bahwa segala kekuatan yang dimiliki manusia diciptakan oleh Tuhan. Kekuasaan Tuhan tidaklah mutlak, melainkan sudah terbatas dikarenakan beberapa faktor. Diantara faktor yang membatasi kekuasaan Tuhan ialah kebebasan yang telah diberikan kepada manusia, hukum alam (sunnatullah) yang tidak akan mengalami perubahan, norma-norma keadilan, dan kewajiban Tuhan terhadap manusia. Menurut Muktazilah, manusia diciptakan Tuhan sekaligus memiliki kemampuan menciptakan perbuatannya baik atau buruk.
Muktazilah mengatakan bahwa problematika takdir dan kebebasan kehendak berkaitan erat dengan prinsip keadilan Tuhan yang mereka kembangkan. Mereka menetapkan bahwa keadilan Tuhan ditujukan kepada hikmah yang bisa diketahui oleh akal dan dimaksudkan untuk merealisir kebaikan dan yang terbaik. Keadilan Allah menolak dari memberi kewajiban (taklîf) kepada seseorang yang tidak mampu ia lakukan atau meng-hisâb apa yang dilakukannya atas paksaan dari-Nya. Untuk itu pada umumnya mereka menolak secara tegas prinsip jabariah. Mereka me- Mahasucikan Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan jelek. Manusia ialah pelaku atas perbuatannya dengan kekuasaan (qudrah) dan kemampuan (istitâ‘ah) yang diberikan Tuhan kepadanya.
Pandangan ini mengandung sikap berpegang pada kekuasaan dan perhatian Allah. Akhirnya manusia harus memilih apa yang dilakukannya, karena perbuatan itu lahir dari niatnya dan merupakan salah satu hasil kehendaknya. Namun hal ini bukan berarti manusia bermaksiat kepada Allah secara terpaksa atau bisa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Manusia hanya terbatas oleh kodratnya sebagai manusia.
Dengan memegang prinsip seperti demikian, bukan berarti Muktazilah tidak mempercayai takdir Tuhan, melainkan mereka mendefinisikannya dengan cara yang berbeda dengan Jabariah. Pendefinisian mereka kurang lebih sesuai dengan apa yang dikatakan Quraish Shihab bahwa jika dikatakan Allah telah menakdirkan sesuatu berarti Allah telah memberi kadar, ukuran, atau batas tertentu dalam diri, sifat, atau kemampuan maksimal makhluk-Nya. Istilah takdir mirip dengan sunnatullah atau hukum alam, tetapi takdir setingkat diatasnya karena hukum-hukumnya tidak hanya terjadi pada alam, melainkan juga pada hukum-hukum kemasyarakatan.
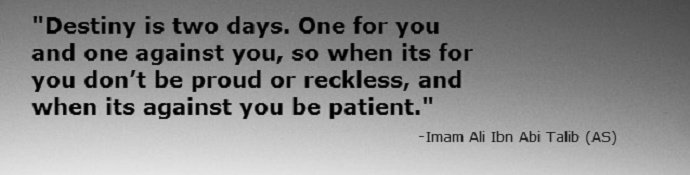
Asy‟ariah
Aliran Asy‟ariah muncul sebagai respon yang „menandingi‟ kekuatan Muktazilah yang pada masa itu disokong oleh para Khalifah Abbasiyah, khususnya al-Ma‟mun yang menjadikan Muktazilah sebagai mazhab resmi negara. Sesuai namanya aliran ini didirikan oleh Imam al-Asy‟ari yang dilahirkan di Basrah (Irak) pada 260 H/873 M dan meninggal pada 324 H/935 M.116 Sedang kan kata
„Asy‟ariah‟ ditujukan kepada para murid dan pengikut dari Imam al-Asy‟ari itu sendiri.
Al-Asy‟ari tumbuh dan dididik dalam lingkungan Muktazilah. Ia nyaris tidak pernah berontak dari pemikiran Muktazilah hingga kegelisahan mulai menghinggapinya. Hal ini terjadi pada usianya yang keempat puluh di mana secara terbuka ia mengumumkan bahwa ia tidak lagi mengikuti pemikiran-pemikiran Muktazilah dan sebagai konsekuensinya ia akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dari mazhab lamanya itu.
Jika Muktazilah muncul sebagai respon atas pertentangan kaum Khawarij dan Murji‟ah maka Asy‟ariah muncul sebagai tanggapan atas dua kutub ekstrim yang ada pada saat itu—walaupun sering dikatakan lebih dekat kepada Jabariah. Aliran yang pertama adalah Muktazilah yang terlalu memuja akal pikiran dan kaum hasywiyah (antropomorpis) yang hanya memegangi secara tekstual nash-nash agama dengan meninggalkan jiwanya yang hampir menyeret Islam ke dalam kejumudan. Jalan tengah tersebut dapat diterima oleh mayoritas kaum Muslimin.
Penerimaan kaum Muslimin terhadap ajaran al-Asy‟ari bukan tanpa alasan, melainkan diikutii oleh beberapa faktor yang mendukungnya.
-
Pertama, kaum Muslimin pada saat itu sudah bosan dengan perbedaan dan pertentangan mengenai persoalan bahwa al-Quran adalah makhluk yang dicetuskan oleh aliran Muktazilah yang berakibat kebencian mereka terhadap aliran tersebut.
-
Kedua, sosok Imam al- Asy‟ari yang ulung dalam perdebatan dan memiliki ilmu yang cukup mendalam, terkenal juga sebagai seorang yang saleh dan takwa, sehingga dapat menarik banyak orang dan mendapat kepercayaan mereka.
-
Ketiga, sejak masa al-Mutawakkil (tahun 232H) pemerintahan telah meninggalkan aliran Muktazilah. Sebagaimana suatu semboyan bahwa agama raja adalah agama rakyat dan hal ini tidak terkecuali pada kondisi Islam saat itu.
-
Keempat, Imam al-Asy‟ari memiliki pengikut-pengikut yang kuat yang selalu menyebarkan ajaran-ajarannya dan memberikan alasan untuk itu. Kelima, pemerintahan Bani Buwaih yang bercorak Syi‟ah dan yang menjadi tulang punggung aliran Muktazilah telah digantikan dengan pemerintahan Turki Seljuk yang bercorak Sunni dan menyokong aliran Ahlussunnah.
Dalam problematika takdir, al-Asy‟ari berada diantara paham Jabariah dan Muktazilah. Jika Jabariah mengatakan manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dan Muktazilah berpegang bahwa manusia dapat melakukan perbuatan atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya, maka al-Asy‟ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh (kasb) suatu perbuatan.
Teori yang dikenal dengan kasab inilah yang menjadi fokus pembahasan Asy‟ariah mengenai takdir dan perbuatan manusia. Teori inilah yang menjadi sasaran kritik baik dari ulama Islam masa modern maupun para cendekiawan Barat yang menurut mereka ajaran mengenai kasab ini mengidentikkan Asy‟ariah—sebagai golongan terbesar umat Islam—dengan paham predeterminasi atau jabariah.
Al-Asy‟ari mengatakan bahwa semua perbuatan, baik maupun buruk, diciptakan oleh Allah. Tidak ada keraguan sama sekali dalam masalah ini. Merupakan kesalahan tersendiri jika mengatakan bahwa orang kafir itu menciptakan sendiri perbuatannya, karena seseorang tidak menciptakan kecuali apa yang dituju dan diinginkannya. Kekafiran merupakan sesuatu yang rusak dan jelek, tidak patut untuk diinginkan, dan kekafiran tidak mungkin terjadi tanpa kesenga-jaan dari penciptanya. Pada hakikatnya, yang bukan pencipta tidak boleh men-cipta. Sehingga kemungkinan penciptanya tinggal Allah semata. Di sini al-Asy‟ari ingin menegaskan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang terjadi pada manusia justru tidak sesuai atau kebalikan dari kehendaknya dan tidak mungkin ia sebagai penciptanya selama Iradah (kehendak Tuhan) sebagai satu-satunya sumber aksi. Allah menakdirkan dan menentukan perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi tidak berarti Dia memerintahkan agar hal itu dilakukan.
Al-Asy‟ari mengatakan bahwa manusia memiliki kasab dan ikhtiar. Kasab berarti semata-mata hubungan qudrah dan kehendak manusia dengan perbuatan, sedangkan perbuatan itu merupakan ciptaan Allah, karena qudrah manusia sama sekali tidak bisa berpengaruh terhadap yang dikodratinya, karena ia sendiri ialah makhluk Allah. “Allah menjalankan sunnah-sunnah-Nya dengan menciptakan— bersamaan dengan qudrah yang baru—perbuatan yang dikehendaki dan disengaja akal manusia.” Kasab dan ikhtiar ini memiliki keterkaitan erat dengan hisâb (pembalasan) dan menurut al-Asy‟ari, manusia dihisab karena kasab dan ikhtiarnya.
Imam al-Haramain al-Juwaini—seorang tokoh besar Asy‟ariah—mengkritik sudut pandang al-Asy‟ari yang menegaskan bahwa semua perbuatan diciptakan oleh Allah, karena tidak ada Pencipta selain-Nya. Al-Juwaini berpendapat bahwa manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri dengan cara menciptakan kemampuan- kemampuan (qudrah) untuk itu.
Dengan teori ini, perbuatan-perbuatan itu tidak disifati sebagai objek qadar Allah, karena satu objek qadar (maqdûr) tidak bisa berhubungan dengan dua qudrah. Pada diri manusia terdapat qudrah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Qudrah ini merupakan salah satu aksidensia, padahal aksidensia tidak bisa tetap dalam dua masa karena ia menyertai perbuatan dan berakhir dengan berakhirnya perbuatan itu. Qudrah ini memiliki bukan hanya satu maqdûr (objek qudrah), karena Allah menciptakan qudrah untuk berbuat dan qudrah untuk tidak berbuat pada diri seseorang. Selanjutnya al-Juwaini menisbahkan perbuatan-perbuatan mutawallidah kepada pelakunya dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini merupakan kritik terhadap pandangan Muktazilah yang juga dapat diambil dari krtitik yang dilakukan Ibn Rawandi, seorang tokoh Muktazilah, terhadap teori tawallud Muktazilah.
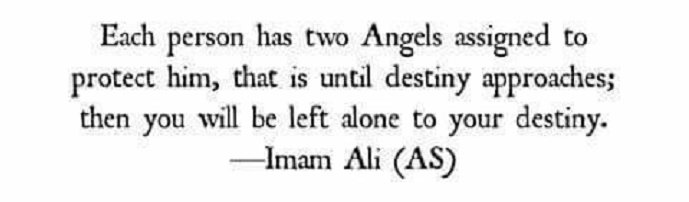
Matudiriah
Aliran Matudiriah, sesuai namanya, ialah para pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi yang dilahirkan di daerah Samarkand (termasuk daerah Uzbekistan). Al-Maturidi hidup sezaman dengan al-Asy‟ari dan meninggal pada 333 H. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mambangun paham teologinya, yakni membendung dan melawan paham Muktazilah. Jika al-Asy‟ari membangun mazhabnya di Bashrah dan Irak pada umumnya, maka al-Maturidi menghadapi Muktazilah di negerinya, yakni Samarkand dan Iran pada umumnya.
Dalam menyelesaikan problematika takdir, al-Maturidi berusaha terlebih dahulu untuk mensucikan keadilan, ilmu, dan kehendak Allah, sekaligus memperkokoh prinsip taklif dan tanggung jawab. Al-Maturidi mengatakan bahwa masing-masing orang tahu bahwa dirinya bebas memilih apa yang dilakukannya; ia adalah pelaku yang kâsib (memiliki kasab).
Perbuatan-perbuatan manusia, walaupun merupakan kasab baginya, juga diciptakan oleh Allah. Perbuatan manusia itu ialah “karya bersama” manusia dengan Tuhan. Allah yang menciptakan dan manusia yang mengkasabnya. Semua ini tentunya merupakan pangkal dari perbuatan-perbuatan ikhtiariah, sedangkan perbuatan-perbuatan individual berasal dari Allah semata.
Berbeda dengan al-Asy‟ari, kasab menurut al-Maturidi berarti kesengajaan (al-qasd) dan ikhtiar. Kasab merupakan proses (amal) positif yang mendahului aksi, sedangkan kasab al-Asy‟ari semata-mata kebersamaan qudrah haditsah (kemampuan temporal) dengan maqdur (objek qadar), karena kasab di sini (baca: al-Asy‟ari) merupakan persoalan negatif yang terjadi bersama dengan aksi (tidak mendahuluinya).
Dalam Maturidiah, al-qasd (unsur kesengajaan) merupakan salah satu unsur penting bagi kebebasan kehendak. Al-qasd merupakan pangkal bagi taklif (perintah agama), prinsip bagi pahala dan dosa, juga pujian dan celaan. Jika seseorang berniat melakukan perbuatan baik, maka Allah pun menciptakan kemampuan (qudrah) pada dirinya agar bisa melakukannya dan berhak menerima pahala karena niatnya itu. Sebaliknya jika ia berniat melakukan perbuatan jelek, maka Allah menciptakan kemampuan pada dirinya agar bisa melakukannya dan ia berdosa karena niatnya itu.
Al-Qasd itu murni, tetapi merupakan amal manusia. Al-qasd memang merupakan amal hati, tetapi mengakibatkan pengaruh-pengaruh eksternal. Perbuatan itu sendiri tidak mengkonsekuensikan pahala atau dosa tetapi al-qasd dari seseoranglah yang mengkonsekuensikan pahala dan dosa, dengan argumen bahwa orang yang tidak memiliki al-qasd tidak terkena taklif seperti anak kecil dan orang yang sedang tidur. Perbuatan itu sendiri baik jika dimaksudkan untuk melakukan kebaikan dan menjadi buruk jika dimaksudkan untuk melakukan kejelekan.
Al-Qasd harus disertai kemampuan untuk berbuat, yakni yang disebut istitâ‘ah. Al-Maturidi membagi istitâ‘ah menjadi dua macam, yaitu
-
Istitâ‘ah mumkinah (kemampuan yang mungkin)
Istitâ‘ah mumkinah berarti keselamatan sebab, alat, dan anggota tubuh yang kesemuanya merupakan pemberian dari Allah yang berfungsi mem-bantu seseorang untuk melakukan perbuatan. Ia harus ada sebelum seseorang melakukan perbuatan, tidak ada taklif tanpa istitâ‘ah ini.
-
Istitâ‘ah muyassirah (kemampuan yang memudahkan).
Istitâ‘ah muyassirah berarti kemampuan temporal (qudrah haditsah) yang menyebabkan manusia bisa berbuat. Kemampuan ini diberikan Allah ketika menusia berniat melakukan suatu perbuatan, karena qudrah ini bersamaan dengan aksi tetapi juga selalu baru dan setiap aksi ada qudrah-nya sendiri. Jadi, ada istitâ‘ah yang mendahului perbuatan dan ada pula yang bersamaan dengan perbuatan.
Jika dilihat dari keterangan di atas, maka posisi Maturidiah dalam permasalahan takdir berada diantara al-Asy‟ari dan Muktazilah. Disebut al-Asy‟ari di sini dikarenakan diantara tokoh Asy‟ariah pun terdapat pertentangan dengan pendapat al-Asy‟ari itu sendiri. Demikian juga dengan Muktazilah. Di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan perdapat yang pada dasarnya bersifat furû‘iyyah (cabang) sehingga masing-masing tokoh dari setiap aliran tidak melenceng jauh dari prinsip pokok alirannya. Satu hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini ialah tidak dapat mengklaim suatu aliran dengan pandangan yang menyudutkan dari sisi negatif atau kekurangan dari suatu pendapat, apalagi klaim bahwa Islam membawa ajaran predeterminisme yang membuat umatnya hanya pasrah terhadap takdir.
Kembali kepada Maturidiah, al-Matudiri mengatakan bahwa kebebasan kehendak tidak bertentangan dengan qadâ‘ dan qadar Allah, karena qadâ‘ pada hakikatnya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan qadar menjadi sesuatu berupa kebaikan atau keburukan yang ada.
Jadi Allah meng-qadâ‘ perbuatan maksiat dan jelek dan meng-qadar-nya. Sedangkan melakukannya bukanlah dari Allah, tetapi berasal dari manusia dengan kemampuan, ikhtiar, dan niatnya. Memang pada akhirnya semua kembali kepada Allah, karena Ia adalah Tuhan dan pencipta segala sesuatu. Tetapi demikian tidaklah pantas—demi sopan santun—untuk mengatakan bahwa Allah adalah pencipta perbuatan-perbuatan maksiat. Dengan demikian, kebebasan kehendak terbatas pada kesengajaan dan niat, yang dari Maturidiah ini dapat dijadikan benang merah dalam lapangan pembahasan yang luas itu (baca: takdir).
Harun Nasution mengatakan bahwa sejak abad kedua puluh terdapat kecenderungan untuk mengangkat kembali paham bercorak rasional yang dibawa oleh Muktazilah, khususnya di kalangan terpelajar Islam. Walaupun demikian aliran Asy‟ariah tetap menjadi mayoritas paham yang dipegang oleh umat Islam. Demi kelengkapan dan kapasitas kajian ini maka akan dibahas beberapa pendapat mengenai takdir dari para ulama maupun cendekiawan dari masa modern dan kontemporer.
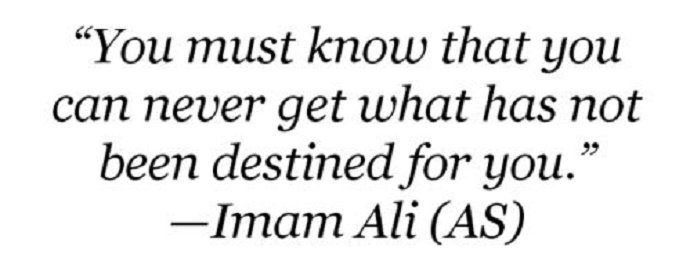
Pemikiran Modern
Pemikiran-pemikiran al-Afghani menjadi cikal bakal perkembangan pemikiran modern yang secara khusus muncul pada abad kesembilan belas. Diantara para mujaddid dan reformis yang mengumandangkan semangat kebangkitan Islam, Muhammad Abduh adalah tokoh terdepan. Dalam menyikapi problematika takdir Muhammad Abduh mengatakan bahwa ada dua perkara fundamental yang merupakan tiang kebahagiaan dan pembimbing segala perbuatan manusia.
-
Pertama, bahwa manusia memiliki usaha yang bebas dengan kemauan dan kehendaknya untuk mencari jalan yang dapat membawanya kepada kebahagiaan.
-
Kedua, bahwa qudrah Allah adalah tempat kembalinya segala makhluk. Diantara kekuasaan tersebut ialah bahwa Allah sanggup memisahkan manusia dari apa yang diinginkannya dan tidak seorang pun selain-Nya yang bisa menolong manusia dalam apa yang tidak mungkin dicapainya.
Abduh mengatakan bahwa setiap individu bisa mempertimbangkan perbuatan-perbuatan ikhtiarnya, menghukum dengan akalnya, dan merinci dengan kehendaknya. Jika telah mantap dengan suatu pandangan, seorang individu akan melaksanakannya dengan kehendaknya semata. Semua itu merupakan fenomena yang dapat dirasakan semua orang dan tidak bisa dipungkiri.
Semua manusia berjalan di atas jalurnya, sehingga ia dapat benar dan salah, tanpa mesti terlebih dahulu mengetahui apa yang ditetapkan dalam ilmu Allah atau mengerti secara penuh apa yang telah tertulis sejak azali. Abduh mengatakan bahwa merupakan kesia-siaan jika seseorang atau suatu paham membentengi diri dengan prinsip takdir yang determinis untuk membela dosa yang dilakukan atau menghindarkan diri dari tanggung jawab yang mesti dipikul. Kadang manusia berhasil, kadang pula gagal. Kegagalan manusia dapat dikarenakan keterbatasan dan administrasi yang buruk atau terkadang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Dengan kata lain Abduh menawarkan untuk mengakui adanya faktor yang berada di atas kemampuan manusia, tetapi hal ini tidak menjadikan manusia untuk menyia-nyiakan wujudnya dan faktor ini juga tidak membelenggu niat dan kehendak manusia.
Syaikh Mahmud Syaltut—guru besar al-Azhar—dengan tegas mengatakan bahwa yang disebut takdir (baca: qadâ dan qadar) semata-mata ialah undang-undang (aturan) yang kekal yang tidak pernah terjadi kekeliruan di dalamnya. Diantara undang-undang tersebut ialah bahwa manusia diciptakan berikut kebebasan untuk memilih perbuatannya tanpa didorong ataupun dipaksa.
Dengan kebebasan tersebut manusia dapat memilih antara petunjuk atau kesesatan maupun kebaikan atau kejahatan. Kesempurnaan ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi bukan berarti paksaan atau belenggu kepada manusia untuk memilih pilihannya. Lantaran demikian Islam melarang manusia untuk menyimpang dari garis-garis perintah dalam akidah maupun agama dan melontarkan alasan mengenai penyimpangan tersebut dengan dalih takdir. Jika terjadi demikian maka menurut Syaltut seluruh kewajiban agama menjadi batal, demikian pula halnya dengan risalah para nabi, penurunan kitab-kitab, seruan mengajak kepada agama Allah berikuta segala kewajibannya, janji Allah berupa pahala untuk kebaikan, dan balasan siksa bagi pelaku kejahatan.
Fazlur Rahman mengakui bahwa di akhir Zaman Pertengahan terdapat kecenderungan yang kuat dalam masyarakat Muslim dengan paham predeterminisme. Menurutnya predeterminisme ini tidak bersumber dari ajaran al-Quran, tetapi disebabkan faktor-faktor yang sedemikian banyak. Hal inilah yang mempengaruhi pandangan orang-orang Barat tentang Islam. Namun demikian Rahman mengatakan bahwa ajaran predeterminisme ini merupakan kesimpulan yang salah dan terlalu simplistis.
Rahman mengatakan bahwa qadar itu sebenarnya berarti “memberi ukuran atau keterhinggaan”. Ide yang terkandung di dalamnya ialah bahwa hanya Allah saja yang mutlak tidak terbatas. Setiap yang selain-Nya memiliki “keterbatasan” dalam setiap potensi yang telah digariskan untuknya. Setiap potensi tersebut memiliki keterbatasan meskipun dalam konteks manusia jangkauan potensi-potensi itu sangat luas. Al-Quran tidak membicarakan akltualisasi potensi-potensi ini, melainkan hanya berbicara mengenai potensi-potensi tersebut. Setiap makhluk diciptakan dengan potensi-potensi dan hukum tingkah laku atau hidayah sehingga ia menuruti sebuah pola tertentu dan menjadi sebuah faktor di dalam kosmos. Manusia merupakan satu- satunya kekecualian dalam hukum universal ini karena diantara semua makhluk hanya manusialah yang diberikan kebebasan untuk menaati ataupun mengingkari perintah-Nya.
Dari beberapa pandangan dari zaman modern dan kontemporer tersebut dapat dilihat adanya kecenderungan untuk “mengembalikan” ajaran mengenai takdir kepada hukum alam dengan tingkatan yang lebih tinggi dari hukum yang hanya bersifat kosmos atau pergerakan yang nyata. Terdapat kecenderungan untuk menyadarkan umat Islam bahwa setiap manusia telah diberikan potensi yang sedemikian besarnya tanpa ada paksaan atau belenggu dalam perbuatan maupun keinginannya. Manusia memiliki keinginan yang bebas. Pada titik inilah—seperti apa yang dikatakan Harun Nasution—seakan-akan konsep Muktazilah tentang takdir menjadi solusi bagi keterbelakangan umat Islam secara garis besar. Dengan perkataan ini bukan berarti Muhammad Abduh dan yang lainnya merupakan pengikut Muktazilah, tetapi yang dapat disimpulkan ialah bahwa kaum Muktazilah telah memberikan suatu warisan yang berharga bagi perkembangan pemikiran dalam Islam itu sendiri.
Referensi
- Arifin Jami‟an, Memahami Takdir (Gresik: CV Bintang Pelajar, 1986).
- M. Taqi Misbah Yazdi, Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan. Penerjemah: Ahmad Marzuki Amin (Jakarta: al-Huda, 2005).
- Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan, 1995), cet. III.
- Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur`an. Penerjemah: Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1996), cet. II.
- Abbas Mahmud al-Aqqad, Filsafat Qur‘an. Penerjemah: Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).
- Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid II (Jakarta: UI-Press, 2002), edisi II.
- M. Abdul Hye, , A History of Muslim Philosophy (Delhi: Low Price Publication, 1995), cet. IV.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Aqidah Seorang Muslim. Penerjemah: Salim Bazemool (Solo: Pustaka Mantiq, 1994).
- Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah , Analisa, Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986).
- Muhammad Abduh, „Perbuatan-perbuatan Manusia‟ dalam Pandangan Para Ahli Pikir tentang Takdir dan Ikhtiar, ed. Mohammad Thalib (Surabaya: Bina Ilmu, 1977).
- Mahmud Syaltut, Islam, Akidah,dan Syari‘ah edisi revisi. Penerjemah: Abdurrahman Zain (Jakarta: Pustaka Amani, 1998).