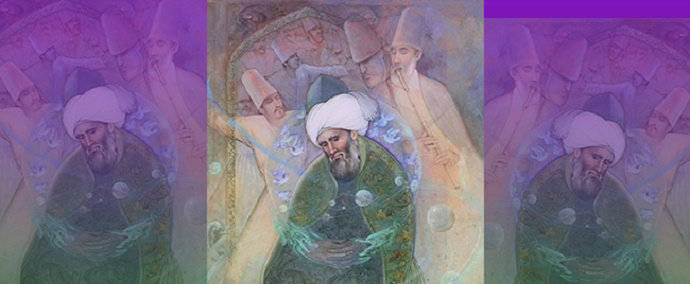Ajaran-ajaran Al-Hallaj, khususnya yang berbicara tentang tasawuf ada tiga, yaitu: penjelmaan Tuhan ke dalam diri manusia ( ḫulûl), asal usul kejadian alam semesta dari Nûr Muhammad (cahaya Muhammad) dan konsep kesatuan agama ( waḫdaṯ al-adyan).
Ajaran ḫulûl ini menjelaskan tentang keadaan “kerasukan Tuhan” atau Tuhan menitis pada diri seseorang yang telah mampu menyatu dengan-Nya. Kemungkinan prestasi ini dapat dicapai karena dalam diri manusia terdapat dua potensi sifat dasar, yakni unsur nasut (kemanusiaan) dan unsur lahut (ketuhanan), yakni ruh manusia yang berasal dari ruh Tuhan, yang sesuai dengan penegasan
Al-Quran surat Shaad: 71-72, sebagai berikut:
“ (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah Kusempurnakan kejaadiannya dan Kutiupkan kepada ruh-Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya.
Nasut mengandung tabiat kemanusiaan, baik yang rohani maupun jasmani. Karenanya Tuhan tidak dapat bersatu dengan tabiat ini, kecuali dengan jalan “menjelaskan” diri atau menurut istilah Massignon, “dengan jalan merasuknya Ruh Suci yang mengambil tempat dalam ruh jasmani”.
Dalam sebuah syair Al- Hallaj berujar sebagaimana dikutip oleh Sayyid Husein Nasr:
“Jika kau telah tiada dari hatimu, Dia akan menempatkan diri-Nya di situ.
Dan tanda-tanda-Nya akan tergelar di tempat wahyu yang tinggi letaknya, yang terjaga dengan baik.
Dan akan tercipta kasih ketuhanan yang tenaga pendengarannya tak kenal lelah dan yang hikayat dan sajak-sajaknya akan terdambakan benar-benar”.
Bagi Al-Hallaj, titik tolak “prestasi” ini pada diri manusia ada dalam cinta. Manusia mencintai Tuhannya, dan Tuhan pun akan mencintai manusia. Al-Hallaj menulis ungkapan cintanya dalam surat-surat yang sering memiliki bentuk dialektik khas pemikiran mistik. Ungkapannya paradoksal, yang menurut Annemarie Schimmel, justru membukakan rahasia hubungan cinta antara manusia dan Tuhan, yaitu
“Jangan biarkan dirimu kena tipu daya Allah, dan jangan memutuskan harapanmu dari-Nya, jangan mengharapkan cinta-Nya, dan jangan mundur dari cinta terhadap-Nya”.
Ungkapan yang lain dapat disimak dalam puisi indahnya:
“Aku yang kucinta
Dan yang kucinta Aku pula Kamu dua jiwa padu jadi Satu Dan jika kau lihat aku
Tampak pula Dia dalam pandanganmu Dan jika kau lihat Dia
Kami dalam pandangannmu tamak nyata.
Bagi Al-Hallaj, cinta ketuhanan bukan sekedar kepatuhan, tetapi: “Cinta berarti bahwa kau tetap berdiri di depan kekasihmu, ketika kau tidak menyandang sifat-sifat lagi dan ketika penyifatan datang dari penyifatan-Nya saja. Cinta dilaksanakan melalui penderitaan, menerima dan mendambakannya, karena penderitaan itu ia sendiri. Bukan berarti Al-Hallaj mengajarkan penghancuran, sebab penderitaan yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai positif, yang dapat digunakan manusia untuk memahami isyq (cinta). Dan kata isyq, dengan konotasi “cinta birahi penuh gairah”, manurut Al-Hallaj, berasal dari cinta ilahi yang dinamis dan merasuk ke dalam kalbu. Syairnya berbunyi:
“Kau antara kalbu dan denyutku, berlalu.
Bagaikan air mata menetes dari kelopakku. Bisik-Mu pun tinggal dalam relung hatiku.
Bagai ruh yang hulul dalam tubuh jadi satu.
Ketika terjadi ḫulûl pada diri manusia, Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki yang dipergunakannya untuk mendengar, melihat, memegang dan berjalan. Artinya, semua yang ada dikehendaki atas perintah Allah. Maka semua aktivitas manusia merupakan aktivitas-Nya, dan semua urusan adalah urusan Allah. Tampaknya pikiran ini diambil dari hadits qudsi Nabi Muhammad:
“… maka apabila Aku (Tuhan) mencintainya (manusia), diri-Ku menjadi pendengarannya, diri-Ku menjadi tangannya dan diri-Ku menjadi kakinya"
Itulah sebabnya Al-Hallaj menggambarkan ḫulûl- nya sebagai berikut:
“And I said: If you do know Him, then know His signs. I am His sign ( tajalli) and i am the Thruth ! And this is because I have not ceased to realize the Thruth!.
Namun, ternyata ḫulûl dalam pandangan Al-Hallaj begitu kontradiktif. Terkadang dinyatakannya bersama penyatuan, namun di pihak lain dia negasikan pernyataan itu. Bahkan secara tegas dia meniadakan unsur-unsur antropomorfis konsepsi Tuhan. Pandangan ini terlihat jelas dalam penegasannya: “Allah mandiri dalam Zat maupun sifat-Nya dari zat makhluk. Dan Dia tidak sekali-kali menyerupai makhluk-makhluk-Nya. Lebih gamblang lagi dia berkata:
“Seperti halnya nasutku terlebur dalam lahut-Mu, tanpa berpadu dengannya: lahut-Mu menguasai nasutku tanpa berpadu dengannya”.
Terhadap ajaran ini, al-Taftazani banyak mencatat tanggapan dari berbagai pihak. Dari kalangan orientalis, Mueller dan d’Horbelot berpendapat bahwa Al- Hallaj secara diam-diam adalah seorang “Kristen”. Sedangkan Thoulk menuduhnya mempunyai kepribadian kontradiktif, tetapi dapat diinterpretasikan bahwa dia dalam keadaan fana, atau di bawah pengaruh aliran filsafat Neo Platonisme. Adapun Browne memberinya gelar “ seorang konspirator yang teguh dan berbahaya”. Dan Massignon berpendapat bahwa Al-Hallaj adalah seorang kontroversial dan pada saat yang sama, dia juga seorang sufi yang berusaha mengkompromikan akidah Islam dengan filsafat Yunani di atas landasan pengalaman mistik. Sedang tanggapan al-Taftazani sendiri, bahwa konsep ḫulûl al-Hallaj didominasi keadaan fanâ’ , yakni sirnanya sifat kemanusiaan ke dalam keabadian ingatan akan Tuhan, sehingga dia mengucapkan ungkapan-ungkapan ganjil, yang secara harfiah merupakan ungkapan-ungkapan ingkar. Maka tampaknya Al-Hallaj benar-benar terpengaruh oleh berbagai kebudayaan seperti filsafat Yunani, pikiran-pikiran Persia, aliran Syi’ah dan ajaran Kristen.
Namun patut pula diduga bahwa ḫulûl Al-Hallaj berciri figuratif ddan bukannya riil. Hal ini dikukuhkan oleh ucapannya sendiri, sebagaimana dikutip oleh al-Sulami, “ Kemanusiaan tidak terpisah dari-Nya dan tidak berhubungan dengan-Nya”. Itu berati menurut Al-Hallaj, manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan citra-Nya adalah tempat teofani Tuhan (al-tajalli al-ilahhi). Jadi, dia berhubungan dengan Allah dengan tanpa berpisah dari-Nya. Tetapi teofani Allah kepada hamba-Nya, atau muncul-Nya dari segi citra-Nya kepada manusia, tidak berarti terjadinya hubungan dengan manusia secara riil-indrawi. Sehingga hubungan tersebut sekadar kesadaran psikis yang berlangsung pada kondisi fana, atau ketika terleburnya nasut ke dalam lahut.
Namun bagaimanapun, ajaran inilah yang terpaksa ditebusnya dengan harga yang sangat mahal, yakni dengan jiwa, raga, dan harga dirinya. Dia dituduh telah berpaham monisme atau panteisme, yang termasuk bid’ah dan merusak akidah tauhid. Terhadap tuduhan ini, Muhammad Yusuf Musa menegaskan ḫulûl Al- Hallaj bukan berbentuk monisme tetapi berbentuk dualisme, yaitu paham yang mengakui dua wujud yang berbeda: al-Khaliq ( sang pendipta) dan makhluk ( yang diciptakan). Apalagi dalam banyak penegasannya, Al-Hallaj tetap mengakui adanya perbedaan antara Tuhan dan makhluk-Nya.
Junayd memahami sepenuhnya bahwa pengalaman dan pemikiran mistik tidak bisa diuraikan dengan akal dan bahwa berbahaya untuk berbicara secara terbuka mengenai rahasia terdalam iman di hadapan orang-orang awam (terutama sekali karena kelompok-kelompok ortodoks memandang kegiatan para sufi dengan kecurigaan yang semakin besar).
Al-Quran dan Hadits dengan jelas menyebutkan bahwa “ inti” makhluk adalah “bentuk lain” dari Allah. Hubungan antara Sang Pencipta dan yang diciptakan bukanlah merupakan salah satu persamaan, tetapi “bentuk lain”. Benda yang diciptakan adalah bentuk laian dari penciptaannya. Hal ini tentunya berbeda dengan paham-paham tasawuf filosofis yang terkenal dengan ungkapan-ungkapan keganjilannya. Kaum sufi Sunni menolak ungkapan-ungkapan ganjil seperti yang dikemukakan Abu Yazid Al-Busthami dengan teori fana’ dan baqa- nya, Al-Hallaj dengan konsep hulûl- nya.
Ungkapan-ungkapan itu keluar dari batas-batas etika syara’, tidak pantas di hadapan Tuhan Yang Mahasuci, atau dari ungkapan-ungkapan itu merembes paham ateisme.
Penolakan Imam Al-Junaid Terhadap Paham Pantheisme ( Ḫulûl )
Imam Al-Junaid menyatakan bahwa Allah tersucikan ( munazzah) dari segala kesalahan dan Dia tidak Ḫulûl (menitis) di dalam entitas wujud apa pun. Karenanya, setinggi apapun taraf spiritual yang dicapai seseorang dan sebanyak apapun hakikat yang tersingkap dihadapannya, ia tetap tidak diperbolehkan sama sekali keluar dari martabat kehambaan kepada Allah dengan mengklaim sebagai titisan Tuhan. Sebaliknya, penghambaannya kepada Allah justru harus semakin nyata. Al-Junaid mengatakan: “Tidak ada seorang pun yang mencapai derajat hakikat kecuali ia wajib membatasi diri dengan hak-hak penghambaan dan hakikatnya, bahkan ia dituntut lebih banyak lagi untuk menjalankan beragam adab (tata krama).
Al-Junaid bersikap tegas dan keras terhadap setiap orang yang mengklaim ḫulûl atau ittiḫâd dari kalangan pseudo-sufi yang secara sepihak dan palsu menisbatkan diri pada tasawuf. Ia mengatakan, “ Andai aku memegang otoritas kekuasaan maka akan kupenggal kepala setiap orang yang menyatakan: “ Tidak ada di sana kecuali Allah karena secara eksplisit pernyataannya ini berkonsekuensi menafikkan makhluk dan menafikkan seluruh tatanan hukum syariat yang berkaitan dengan mereka.”
Meski demikian, Al-Junaid tidak serta-merta mengingkari pernyataan bernada pantheistik yang keluar dari lisan ahl ash-shidq (kalangan sufi sejati) yang tengah mengalami syath (ekstase sufi) lalu mengucapkan perkataan musykil dalam mabuk spiritual atau fana’- nya.
Pendek kata, Al-Junaid tetap konsisten mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi-Nya, dan menolak tegas paham pantheisme ( al-ḫulûl) . Ia hanya cenderung memaafkan kaum sufi sejati (ash-shâdiqin) yang mengucapkan perkataan musykil ketika tengah fana’ atau mabuk spiritual, sebagaimana kecenderungannya untuk membedakan antara sufi sejati dan pseudo-sufi.
Penolakan Imam Al-Ghazali Terhadap Paham Ḫulûl
Al-Ghazali menilai negatif terhadap syathahat karena dianggapnya mempunyai dua kelemahan.
- Pertama, kurang memerhatikan amal lahiriah, hanya mengungkapkan kata-kata yang sulit dipahami, mengemukakan kesatuan dengan Tuhan, dan menyatakan bahwa Allah dapat disaksikan. Kedua, syathahat merupakan hasil pemikiran yang kacau dan hasil imajinasi sendiri. Dengan
Penolakan Imam Al-Junaid Terhadap Paham Pantheisme ( Ḫulûl )
Imam Al-Junaid menyatakan bahwa Allah tersucikan ( munazzah) dari segala kesalahan dan Dia tidak Ḫulûl (menitis) di dalam entitas wujud apa pun. Karenanya, setinggi apapun taraf spiritual yang dicapai seseorang dan sebanyak apapun hakikat yang tersingkap dihadapannya, ia tetap tidak diperbolehkan sama sekali keluar dari martabat kehambaan kepada Allah dengan mengklaim sebagai titisan Tuhan. Sebaliknya, penghambaannya kepada Allah justru harus semakin nyata. Al-Junaid mengatakan: “Tidak ada seorang pun yang mencapai derajat hakikat kecuali ia wajib membatasi diri dengan hak-hak penghambaan dan hakikatnya, bahkan ia dituntut lebih banyak lagi untuk menjalankan beragam adab (tata krama).
Al-Junaid bersikap tegas dan keras terhadap setiap orang yang mengklaim ḫulûl atau ittiḫâd dari kalangan pseudo-sufi yang secara sepihak dan palsu menisbatkan diri pada tasawuf. Ia mengatakan, “ Andai aku memegang otoritas kekuasaan maka akan kupenggal kepala setiap orang yang menyatakan: “ Tidak ada di sana kecuali Allah karena secara eksplisit pernyataannya ini
102 Ibid.
berkonsekuensi menafikkan makhluk dan menafikkan seluruh tatanan hukum syariat yang berkaitan dengan mereka.”103
Meski demikian, Al-Junaid tidak serta-merta mengingkari pernyataan bernada pantheistik yang keluar dari lisan ahl ash-shidq (kalangan sufi sejati) yang tengah mengalami syath (ekstase sufi) lalu mengucapkan perkataan musykil dalam mabuk spiritual atau fana’- nya.
Pendek kata, Al-Junaid tetap konsisten mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas bagi-Nya, dan menolak tegas paham pantheisme ( al-ḫulûl) . Ia hanya cenderung memaafkan kaum sufi sejati (ash-shâdiqin) yang mengucapkan perkataan musykil ketika tengah fana’ atau mabuk spiritual, sebagaimana kecenderungannya untuk membedakan antara sufi sejati dan pseudo-sufi.104
Penolakan Imam Al-Ghazali Terhadap Paham Ḫulûl
Al-Ghazali menilai negatif terhadap syathahat105 karena dianggapnya mempunyai dua kelemahan. Pertama, kurang memerhatikan amal lahiriah, hanya mengungkapkan kata-kata yang sulit dipahami, mengemukakan kesatuan dengan Tuhan, dan menyatakan bahwa Allah dapat disaksikan. Kedua, syathahat merupakan hasil pemikiran yang kacau dan hasil imajinasi sendiri. Dengan
hlm:112.
103 Muhammad Fauqi Hajjaj. Tasawuf Islam dan Akhlak. (Jakarta: Amzah, 2013)
104 Ibid, hlm. 113.
105 Ungkapan dan isyarat-isyarat yang mereka sampaikan saat berada dalam keadaan
mabuk ketuhanan dan lenyapnya kesadaran, yang makna-maknanya tidak jelas bagi orang yang belum mencapai kondisi rohani seperti mereka.
demikian ia menolak tasawuf semi filsafat meskipun ia mau memaafkan Al-Hallaj dan Yazid Al-Busthami. Ungkapan-ungkapan yang ganjil itu telah menyebabkan orang-orang Nashrani keliru dalam menilai Tuhannya, seakan-akan ia berada pada diri Al-Masih. 106
Al-Ghazali sama sekali menolak paham ḫulûl dan ittihâd. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang makrifat, yakni pendekatan diri kepada Allah ( taqarrub ilâ Allah ) tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju makrifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Ringkasnya, Al-Ghazali patut disebut berhasil mendiskripsikan jalan menuju Allah SWT. Makrifat menuju versi Al-Ghazali diawali dalam bentuk latihan jiwa, lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian rohani dalam tingkatan- tingkatan ( maqâmât ) dan keadaan ( ahwâl ).
Oleh karena itu, Al-Ghazali mempunyai jasa besar dalam dunia Islam. Dialah orang yang mampu memadukan antara ketiga kubu keilmuan Islam, yakni tasawuf, fiqh, dan ilmu kalam, yang sebelumnya terjadi ketegangan di antara ketiganya.
Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, (Kairo: Musthafa bab Al-Halab,1334), jilid III.
Muhammad Fauqi Hajjaj. Tasawuf Islam dan Akhlak. (Jakarta: Amzah, 2013).
Dengan demikian ia menolak tasawuf semi filsafat meskipun ia mau memaafkan Al-Hallaj dan Yazid Al-Busthami. Ungkapan-ungkapan yang ganjil itu telah menyebabkan orang-orang Nashrani keliru dalam menilai Tuhannya, seakan-akan ia berada pada diri Al-Masih.
Al-Ghazali sama sekali menolak paham ḫulûl dan ittihâd. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang makrifat, yakni pendekatan diri kepada Allah (taqarrub ilâ Allah) tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan menuju makrifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Ringkasnya, Al-Ghazali patut disebut berhasil mendiskripsikan jalan menuju Allah SWT. Makrifat menuju versi Al-Ghazali diawali dalam bentuk latihan jiwa, lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian rohani dalam tingkatan- tingkatan (maqâmât) dan keadaan (ahwâl).
Oleh karena itu, Al-Ghazali mempunyai jasa besar dalam dunia Islam. Dialah orang yang mampu memadukan antara ketiga kubu keilmuan Islam, yakni tasawuf, fiqh, dan ilmu kalam, yang sebelumnya terjadi ketegangan di antara ketiganya.
Referensi :
- Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam, (Jakarta: Pustsaka Firdaus, 2000)
- Fathimah Usman, Wahdat Al-Adyan, (Yogyakarta: Lk iS, 2002).
- Muhammad Fauqi Hajjaj. Tasawuf Islam dan Akhlak. (Jakarta: Amzah, 2013)
- Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, (Kairo: Musthafa bab Al-Halab,1334), jilid III