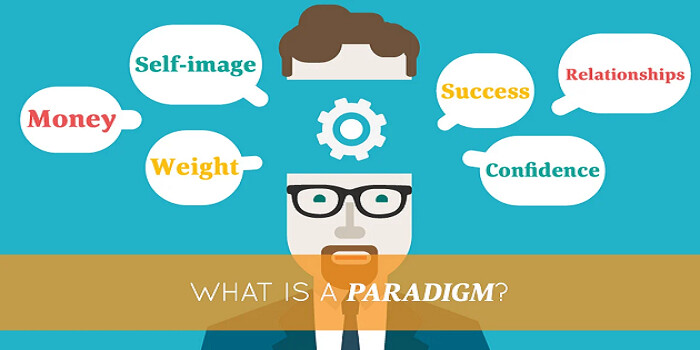Paradigma menurut beberapa pandangan secara umum dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang atas suatu fenomena yang dalam upayanya untuk menjelaskan secara kongkret dan realistis.
Paradigma adalah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia, cara kita melihat dunia [1]. Dalam bahasa inggris, paradigma dapat pula disebut sebagai worldview atau welthanschaung dalam bahasa jerman. Keduanya bermakna pandangan atau persepsi tentang dunia. Dalam beberapa literatur, terma perspektif juga dipakai bergantian dengan paradigma [2]. Dengan timbulnya paradigma baru tentang dunia, timbul pula paradigma baru dalam penelitian serta metode yang digunakan. Paradigma dapat berubah seiring dengan timbulnya pandangan baru, perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan akan merubah cara-cara berpikir dan merangsang imajinasi, harapan, kepercayaan dalam usaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dunia ini.
Istilah paradigma sendiri sebenarnya dipakai pertama kali oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution (1962). Paradigma merupakan terminologi kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang diperkenalkan Khun, meskipun ia tidak merumuskan dengan jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan paradigma itu sendiri[3]. Kritik mendalam Khun adalah pada metode ilmiah (mulai dari observasi, eksperimentasi, deduksi dan konklusi yang diidealisasikan). Dasar klaim ilmu yang obyektif dan universal menurutnya sebagai ilusi. Khun menyatakan paradigmalah yang menentukan jenis-jenis eksperimen ilmuwan, jenis- jenis pertanyaan yang diajukan dan masalah yang mereka anggap penting.
Tanpa paradigma tertentu para ilmuwan bahkan tak bisa mengumpulkan ‘fakta’. Pergeseran paradigma mengubah konsep-konsep dasar yang melandasi riset dan mengilhami standar-standar pembuktian baru, teknik-teknik riset baru serta jalur-jalur teori dan eksperimen baru yang secara radikal tidak bisa dibandingkan lagi dengan cara yang lama[4]. Makna munculnya konsepsi revolusi ilmu adalah perang ilmu yang terjadi sepanjang sejarah untuk menetapkan kekuatan ilmu yang berada pada sisi satu sama lainnya. Tarik menarik ini (antara ilmu yang evolutif dan revolutif) telah menjadi tradisi yang tak kunjung selesai. Dan sebenarnya pula pikiran Khun bukan menolak tradisi ilmu yang telah mapan dan juga tidak menolak tradisi ilmu yang berkembang yang tidak muncul secara evolutif, tetapi terdapat kemungkinan revolusi di dalamnya.
Evolusi Paradigma Penelitian
Paradigma penelitian menurut Sudarma dimulai sejak masa pra-positivimse yaitu periode zaman Aristoteles (305 SM) sampai periode David Hume (1750 SM) selama ribuan tahun orang berpandangan bahwa apa yang terjadi bersifat ilmiah. Paradigma ini menyatakan bahwa peneliti mengamati sebagai pengamat pasif, artinya tidak dengan sengaja memanipulasi lingkungan dan tidak mengadakan eksperimen dengan lingkungan tersebut
Paradigma Positivisme
Setelah masa pra-positivisme timbul pandangan baru, yakni bahwa peneliti dapat dengan sengaja mengadakan perubahan dalam dunia sekitar dengan melakukan berbagai eksperimen. Timbullah apa yang disebut metode ilmiah dan masa ini disebut masa positivisme (paradigm positivism), atau dalam penelitian sering disebut metode kuantitatif. Pandangan ini berpendapat bahwa realitas sebagai suatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indera, dapat dipecah menjadi bagian-bagian, dapat diverifikasi, tidak berubah, dan bebas nilai.
Karakteristik utama penelitian ilmiah dalam metode kuantitatif menurut Sekaran terdiri dari 8 kriteria, yaitu [5]:
-
Purposivenes;penelitian harus mempunyai fokus dan tujuan jelas.
-
Rigor; kecermatan, ketelitian dalam investigasi penelitian.
-
Testability; penelitian menguji secara logis hipotesis.
-
Replicability; hasil uji hipotesis dapat direplikasi.
-
Precision and confidence; membuat desain penelitian yang mendekati realitas.
-
Objectivity; kesimpulan harus berdasarkan fakta dari temuan aktual.
-
Generalability; temuan dapat digeneralisasi dan
-
Parsimony, peneliti menyederhanakan fenomena realitas yang begitu kompleks meliputi sejumlah faktor yang tidak dapat dikendalikan.
Positivisme berpandangan bahwa peneliti harus obyektif, jadi peneliti tidak terlibat secara langsung dari apa yang diamatinya. Apa yang diamatinya dianggap lepas dari pengaruh Si peneliti dengan obyek yang diteliti, penelitan dan hasil penelitian dianggap bebas dari sistem nilai-nilai dari obyek yang diteliti. Peneliti dalam paradigma ini selalu mencoba melakukan pengukuran-pengukuran yang akurat melalui suatu instrumen yang dinamakan kuesioner terhadap realitas sosial yang ditelitinya, sehingga paradigma ini tidak dapat melihat suatu perspektif masalah seacara utuh.[6]
Sebagaimana namanya, yaitu positivisme (sebagai kebalikan dari normativisme), paradigma ini menekankan diri pada kajian sebagaimana adanya (as it is) atau bebas nilai (value-free). Dalam konteks ini, penelitian dipahami hanya sebagai alat untuk menjelaskan (to explain) dan meramalkan (to predict). Dengan tujuan “menjelaskan” dan “meramlakan”, paradigma ini secara implisit berusaha menemukan hukum universal yang ada dalam kajiannya. Menurut paradigma ini, suatu kajian dijelaskan dan diramalkan dalam konteks hukum universal; artinya dapat dipraktikkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dengan kata lain dapat dipraktikkan melintas batas Negara, bahkan melintas batas sistem budaya, agama dan politik. Sehingga paradigma ini banyak memiliki keterbatasan [7].
Keterbatasan paradigma positivisme menurut Sudarma adalah [8]
-
Tujuan penelitian adalah mencapai generalisasi yang dapat digunakan untuk memprediksi tanpa memahami makna yang dalam terhadap suatu obyek secara kontekstual;
-
Positivisme bersifat atomistik, memecah realitas menjadi bagian-bagian, mencari hubungan antara variabel yang terbatas, paradigma ini tidak mencoba memandang realitas secara keseluruhan;
-
Positivisme tertuju kepada kepastian temuan dengan menguji hipotesis, tanpa mengamati “permukaan” atau masalah bagian luarnya tanpa berusaha memperoleh gambaran yang lebih mendalam terhadap suatu obyek yang diteliti.
Paradigma positivisme inilah kemudian yang manjadi aliran mainstream penelitian selama ini. Sifatnya yang kaku dan cenderung hanya mengandalkan suatu ukuran menjadi suatu yang tidak mengherankan jika dalam situasi tertentu timbul suatu aksi dimana para pekerja keilmuan secara tidak sadar berlaku seperti seorang “tukang jahit” yang bekerja mengandalkan hanya dengan satu pola dan ukuran saja.
Hasil akhir dari proses penelitian seperti itu boleh jadi akan serupa dengan baju hanya satu ukuran (one size) yang diharapkan tetap mampu fits for all. Penerapan kerja keilmuan seperti itu dalam ranah ilmu pengetahuan kealaman boleh jadi tidak akan menimbulkan masalah (problematical), pengetahuan sosial (social science studies), implikasi dan risikonya sangatlah besar. Sebab utamanya, karena perilaku manusia yang menjadi obyek kajian ilmu pengetahuan sosial secara hakekat berbeda dengan karakteristik obyek kajian ilmu pengetahuan alam [9].
Dalam penelitian paradigma positivisme, pengetahuan diperoleh secara rasional melalui penalaran dan melalui kajian empiris, sedangkan pandangan epistimologi pengetahuan menurut Sudarma bisa diperoleh melalui penalaran, intuisi, wahyu, kesaksian bahkan keyakinan. Inilah kemudian yang melahirkan suatu konsep pandangan baru yang kemudian disebut dengan multiparadigma.
Pendekatan Multiparadigma dalam Penelitian
Sejarah munculnya istilah multiparadigma pertama kali di gagas oleh Burrell & Morgan (1994) yang menggunakan empat istilah paradigma yaitu paradigma fungsionalis atau positivis, paradigma interpretif, paradigma radikal humanis dan paradigma radikal strukturalis. Hal ini berbeda dengan Chua (1998) yang mengusulkan tiga perspektif paradigma diluar positivisme. Persepektif-persepektif ini adalah perspektif mainstream atau positivis, persepektif interpretif dan persepektif kritis. Sedangkan penulis lain, yaitu Sarantakos (1993), menambahkan satu lagi atas paradigma yang dikemukakan Chua, sehingga menjadi empat, yaitu: (1) positivist paradigm, (1) interpretivist paradigm, (3) critical paradigm, dan (4) postmodernist paradigm.
Muculnya istilah multiparadigma menurut Suyunus [10] di Indonesia berawal dari beberapa orang Indonesia yang menempuh kuliah di Australia pada era tahun 1990 ke atas. Pada saat yang sama pemerintah Indonesia juga mengirim dosen-dosen muda ke berbagai universitas di Amerika baik S2 maupun S3 dengan melakukan pendekatan riset yang dikenal selama ini, riset kuantitatif, yaitu riset yang menggunakan statistik sebagai alat analisis. Sebagian besar riset masih berwarna kuantitatif, sehingga cara riset tersebut lebih mendominasi riset di tanah air.
Cara riset yang diusung oleh alumni dari universitas di Australia khususnya dari University of Wollongong berbeda dari lulusan Amerika, maka muncullah sebutan mainstream untuk riset namun jika hal itu diterapkan dalam ranah ilmu kuantitatif. Disisi lain, para alumni dari Australia mengusung riset anti-mainstream yang disebut multiparadigma. Pendekatan riset multiparadigma adalah berbagai pendekatan riset terhadap obyek riset tertentu dengan menggunakan salah satu dari berabagai paradigma yang ada sebagaimana riset yang di usung oleh Burrell & Morgan, Chua & Sarantakos.
Istilah multiparadigma mulai dikenal ketika Giola dan Pietre (1990) membahas tentang hubungan antara paradigma riset dengan teori organisasi yang dihasilkan serta membahas garis (kontinum) asumsi dalam pemikiran Burrel & Morgan. Keterpakuan seseorang pada satu paradigma saja akan membatasi pemahaman orang tersebut dari paradigma yang lain. Penggunaan satu paradigma secara tunggal akan cenderung menghatarkan orang tersbut pada “pemutlakan” kebenaran yang diperoleh dari paradigma yang digunakannya. Pemutlakan ini akan menciptkan fanatisme paradigma yang ujung-ujungnya hanya mau membenarkan paradigma yang dianutnya, dan sebaliknya selalu menyalahkan paradigma yang lain. Inilah yang kemudian menjadikan seorang peneliti kesulitan untuk menulis di luar “pakem” yang ada pada dirinya, sehingga kreativitas menulis akan “mandeg” dan tidak produktif.
Metode diluar postivisme ini yang kemudian disebut dengan non-positivisme atau non-mainstream, baik yang bersifat interpretif, kritis, atau posmodernisme. Penggunaan metode diluar metode mainstream ini kemudian disebut Fakih [11] sebagai penolakan terhadap “dominasi” representasi penelitian ilmiah positivis. Dominasi positivis atas penelitian ilmiah lanjut beliau adalah bentuk “penguasaan pengetahuan” untuk menerapkan pengetahuan sampai bentuk teknologinya tidak hanya didasarkan ideologi barat tetapi juga didasarkan hasrat untuk mengendalikan berdasar dua asumsi utama scientific methods, yaitu obyectivism dan regulatory.
Obyectivism menurut Mulawarman mensyaratkan peneliti atau ilmuwan sedapat mungkin bertindak netral, berjarak dan tidak melibatkan aspek emosional dan pemihakan. Sedangkan regulatory menempatkan ilmuwan atau peneliti pada posisi sentral dalam analisis sosial maupun proses perubahan sosial. Masyarakat dalam asumsi ini ditempatkan sebagai obyek ilmu. Sebagai subyek, maka ilmuwan atau peneliti dapat legitimasi untuk membangun sendiri agenda maupun tujuan dari perubahan sosial. Oleh karena itu, masyarakat yang diletakkan sebagai obyek harus “menyerahkan diri” untuk diarahkan dan dikembangkan menuju tujuan yang telah ditetapkan.
Paradigma Interpretivisme
Paradigma interpretif diturunkan dari Germanic Philosofical Interest yang menekankan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman. Ilmu pengetahuan, bagi paradigma ini tidak digunakan untuk menjelaskan (to explain) dan memprediksi (to predict), tetapi untuk memahami (to understand). Paradigma interpretif dibentuk berdasarkan asumsi bahwa realitas sosial itu keberadaannya tidak kongkret, melainkan keberadannya dibentuk dari pengalaman subyektif- obyektif masing-masing individu serta bagaimana ia membentuk makna (meaning) atas interpretasi tersebut. Kualitas teori dalam paradigma ini diukur dari kemampuannya untuk memaknai, bukan kemampuannya untuk menjelaskan dan meramalkan.
Paradigma ini memiliki kesadaran kontekstual yang tinggi. Ini terbukti dari ketidakinginan paradigma ini untuk menggeneralisasikan temuan penelitian atau teori. Teori ini tidak memerhatikan pada hukum universal. Dengan demikian, paradigma ini cenderung untuk mengungkapkan temuan-temuan yang sifatnya lokal dan sarat nilai (value laden). Teori yang sarat nilai bukan hal yang “tabu”. Tetapi sebaliknya, nilai yang terkandung dalam teori tersebut menunjukkan “keilmiahan” teori dalam paradigma ini.
Bagi paradigma ini, tidak satupun ilmu pengetahuan yang objektif dan bebas nilai sepanjang dalam proses konstruksi teori terlibat di dalamnya aktor atau manusia. Manusia memiliki subyektifitas, yang secara sadar atau tidak akan masuk dan menyatu dalam proses, maka ilmu pengetahuan secara niscaya akan sarat nilai. Keasadaran konstektual ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang dimiliki oleh paradigma interpretivisme.
Keasadaran ini mencerminkan pemahaman bahwa pada dasarnya suatu kajian dipraktikkan tidak dalam kondisi yang vacuum dari kondisi lingkungan di mana kajian tadi dipraktikkan. Suatu kajian terbentuk dan dipraktikkan melalui proses konstruksi sosial. Proses konstruksi yang demikian ini jelas terkait dengan nilai-nilai lokal dari lingkungannya dan dengan subyektifitas aktor atau manusia dan masyarakat umum.
Paradigma Kritisisme
Jika pada paradigma interpretivisme hanya sebatas pada “manafsirkan”, paradigma kritisisme muncul untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada paradigma pendahulunya, yaitu dengan cara melakukan pembebasan dan perubahan. Tujuan sebuah teori dalam paradigma ini menurut Triyuwono [12] adalah membebaskan (to emancipate) dan melakukan perubahan (to transform). Paradigma ini beranggapan bahwa sebuah teori tidak cukup hanya bisa menafsirkan, tetapi juga harus mampu untuk membebaskan dan mengubah. Tanpa unsur “pembebasan” dan “perubahan” sebuah teori tidak akan pernah dapat disebut sebagai teori kritis.
Paradigma ini menurut Mulawarman [13] dalam melihat realitas bukan pada kenyataan lahir yang dapat dilihat secara indera, tetapi justru pada “ruh” atau gagasan, ilmu sosial lebih dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan, tidak boleh dan tidak mungkin bersifat netral. Paradigma kritis, di sisi lain memperjuangakan pendekatan yang bersifat holistik, serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik.
Oleh karena itu, mereka selalu melihat realitas sosial dalam perspektif kesejarahan. Paradigma kritis memakai baik pendekatan obyektif maupun subyektif untuk menjelaskan tentang perubahan yang selalu terjadi dalam setiap hubungan sosial. Menurut Sarantakos16 makna- makna subyektif adalah relevan dan penting, namun hubungan-hubungan obyektif juga tidak bisa ditolak. Perhatian utama dari paradigma ini adalah membuka mitos dan ilusi, mengekspos struktur yang nyata dan memisahkan paradigma dalam dua bagian, yaitu Radical Humanism dan Radical Structuralism. Radical Humanism memandang perubahan dilakukan lewat consciousness atau kesadaran ,sedangkan Radical Strukturalism memandang perubahan bisa dilakukan lewat perubahan struktur atau sistem.
Pembebasan dan perubahan yang dilakukan oleh paradigma ini tidak saja pada tingkat teori, tetapi juga pada tingkat praktik. Pada tingkat teori, pembebasan dan perubahan dapat dilakukan sejak dari aspek metodologi sampai pada “bentuk” teori itu sendiri. Dalam konteks ini, metodologi kajian katakanlah keimigrasian yang dibangun berdasarkan pada paradigma positivisme yang mendominsasi, maka harus ada suatu gebrakan terhadap dominasi kajian yang mainstream. Paradigma kritis melakukan kritik untuk selanjutnya melakukan perubahan.
Kekuatan paradigma ini terletak pada karakternya yang ingin selalu membebaskan (to emancipate) dan mengubah (to transform). Karakter ini yang membedakan paradigma ini dengan dua pendekatan paradigma sebelumnya. Dengan karakternya ini, suatu kajian akan menjadi dinamis dan kaya, baik pada tingkat teori maupun pada tingkat praktik.
Paradigma Postmodernisme
Realitas suatu kajian pada hakekatnya tidak terbatas pada realitas fisik, tetapi juga psikis. Paradigma ini lahir sebagai antithesis dari modernisme yang positivistik. Paradigma positivisme yang merupakan dasar pola berpikir modernisme hanya memahami realitas pada lapisan materi (fisik) saja. Karena yang dipahami hanya realitas fisik, maka konsep teori yang dibangunnya hanya sebatas dunia materi dan sebaliknya, tidak mampu masuk pada dunia psikis.
Paradigma posmodernisme muncul untuk mengatasi kelemahan paradigma positivisme dengan mencoba memahami realitas secara lebih utuh dan lengkap. Untuk memahami realitas yang kompleks ini, paradigma posmodernisme tidak memiliki pendekatan keilmuan yang baku. Sebaliknya, pendekatannya selalu tidak terstruktur, tidak berbentuk, tidak formal, dan tidak mutlak. Semuanya serba relatif. Untuk memahami realitas yang kompleks memang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan positivistik yang hanya berorientasi pada dunia fisik. Tetapi sebaliknya, pendekatan yang kompleks sangat diperlukan.
Mulawarman [15] menyatakan bahwa postmodernisme muncul akibat kekecewaan terhadap segala atribut yang melekat pada modernitas. Di satu pihak, postmodernisme selalu diikuti dengan hal-hal seperti penyebaran peradaban misal, peradaban barat, industrialiasi, kemjauan teknologi, kapitalisasi, konsumerisme dan lainnya. Namun, di pihak lain, postmodernisme juga melihat rasisme, kesenjangan kemiskinan, diskriminasi, pengangguran sejalan dengan modernisme. Karakter utama postmodernisme terletak pada usaha dekonstruksi yang dilakukan terhadap semua bentuk logosentrisme yang dibuat oleh modernisme. Logosentrisme adalah sistem pola pikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan referensi kebenaran universal dan eksternal [16]
Selain itu, peranan subjek juga sangat penting. Subjek dalam konteks paradigma ini menyatu dengan objek untuk pemahaman yang lebih utuh dan lengkap. Kemampuan subjek di sini tidak hanya terbatas pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Dengan tiga macam kecerdasan ini subjek akan mampu memahami objek yang kompleks untuk konstruksi ilmu pegetahuan yang bersifat lebih komprehensif [17].
Paradigma ini bersifat sangat terbuka dan dapat menerima dan mengombinasikan atau mensinergikan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Pemikiran yang berbeda dapat disatukan dalam bentuk sinergi sebagai misal, nilai-nilai maskulin disinergikan dengan nilai-nlai feminis. Sinergi sebenarnya adalah hukum yang ada di alam semesta ini. Dengan konsep ini, paradigma ini mampu memahami suatu kajian secara komprehensif dikarenakan kemampuannya untuk memahami realitas lebih lengkap bila dibandingkan dengan tiga paradigma lainnya.
Kemajemukan pemikiran atas sinergi yang dilakukan menimbulkan suatu pemahaman atas realitas yang majemuk. Manusia sesungguhnya memiliki kebebasan dalam berfikir sesuai dengan kaidah yang berlaku, dinamis dan berpikir secara holistik. Pemahaman tersebut memiliki konsekuensi bahwa ilmu pengetahuan tidak memiliki sekat secara terpisah-pisah. Dengan demikian ilmu pengetahuan tidak bersifat sistematik, memiliki logika yang majemuk, tidak terpusat, selalu berubah dan bersifat lokal.
Referensi:
- [1] Sudarma, Made. “Paradigma Penelitian Akuntansi Dan Keuangan.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 1, no. 1 (2010): 97–108.
- [2] Ali Djamhuri, “Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2, no. 1 (2011): 147–185.
- [3] Mulawarman, “Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 1, no. 1 (2010): 155–171.
- [4] Ibid.
- [5] Sekaran, Research Methode for Business: A Skill Building Approach. (England: Wiley, 2002).
- [6] Mulawarman, “Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi.”
- [7] Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, Dan Teori, 2nd ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).
- [8] Sudarma, “Paradigma Penelitian Akuntansi Dan Keuangan.”
- [9] Djamhuri, Ali. “Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi.” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2, no. 1 (2011): 147–185.
- [10] Mohamad Suyunus, “Mengikuti Perjalanan Pembawa Bendera: Penyebaran Pemikiran Radikal Riset Akuntansi Multiparadigma,” Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2, no. 1 (2011): 104–125.
- [11] M Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- [12] Triyuwono, Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, Dan Teori.
- [3] Mulawarman, “Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi.”
- [14] S Sarantakos, Social Research (Australia: MacMillan Education, 1993).
- [15] Mulawarman, “Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi.”
- [16] PM Rosenau, Post-Modernisme and the Social Sciences: Insight, Inroads, and Intrusions (New Jersey: Princeton University Press, 1992).
- [17] Triyuwono, Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, Dan Teori; Iwan Triyuwono, “Awakening the Conscience inside : The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants,” Procedia - Social and Behavioral Sciences 172, no. 15th & 16th December, Kuala Lumpur (2015): 254–261,