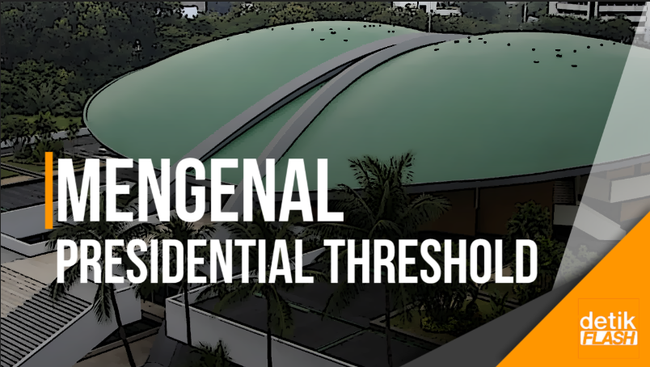
Jawab apa
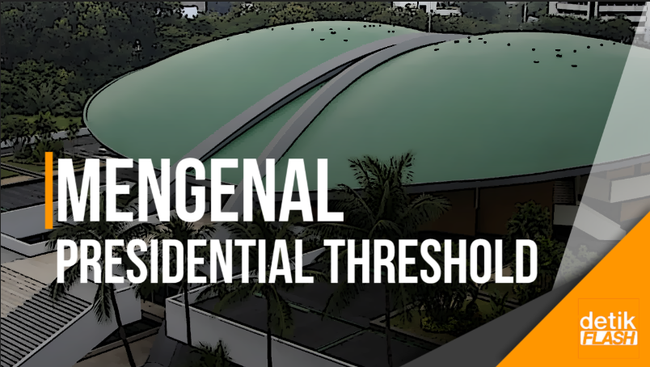
Jawab apa
Sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, polemik tentang penyederhanaan partai politik kembali mencuat ke permukaan. Terakhir, yang menjadi materi perdebatan adalah soal ketentuan parliamentary threshold. Ketentuan ambang batas perolehan kursi parlemen itu tercantum dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilihan Umum harus memenuhi sekurang-kurangnya 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebanyak 11 partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Politik ini menilai ketentuan parliamentary threshold berpotensi membatasi hak politik warga negara. Namun, MK menolak judicial review ketentuan itu. Memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa rencana pengajuan uji materi itu sangat terkait erat dengan kepentingan jangka pendek ke-11 partai politik tersebut. Padahal, semestinya proses pengembangan demokrasi harus diletakkan dalam kerangka kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Karena menurut beberapa pihak sistem pemerintahan presidensial hanya akan dapat berjalan efektif jika didukung oleh sistem multipartai sederhana.
Menurut Sutradara Gintings dan Ryaas Rasyid dalam jurnal Legislasi Indonesia yang ditulis oleh Agung Gunandjar Sudarsa, parliamentary threshold merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen. Perhitungannya dilakukan setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, kemudian dibagi dengan jumlah suara secara nasional. Ketentuan tersebut baru diterapkan dalam Pemilihan Umum 2009 dengan dirumuskan secara implisit dalam Pasal 202 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sudarsa, 2010).
Ketentuan tentang parliamentary threshold atau ambang batas bagi partai politik untuk dapat mendudukkan anggotanya di parlemen menuai pro dan kontra. Memang pada umumnya, baik DPR maupun pengamat berpandangan bahwa parliamentary threshold secara teoritis baik. Namun dari dinamika yang berkembang terkait dengan tingkat kesadaran budaya politik masyarakat tampaknya gagasan ini akan mengalami kendala.
Penerapan parliamentary threshold dinilai beberapa pihak bisa memasung proses demokrasi yang baru berlangsung sejak reformasi 1998. Penerapan parliamentary threshold juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa. Menurut pengamat politik dari Institute Development for Local Parliament (IDELP) Agustinus Tamo Mbapa, di Jakarta, Selasa (23/10), dikuatirkan penerapan parliamentary threshold pada Pemilihan Umum 2009, akan membawa implikasi buruk terhadap proses demokrasi (Batari, 2010).
Penerapan parliamentary threshold di tingkat bawah mempunyai potensi konflik horizontal karena ketika ada calon yang terpilih tetapi karena tidak memenuhi parliamentary threshold, akhirnya calon terpilih itu tidak bisa duduk di parlemen. Misalnya Jumlah Pemilih Terdaftar (DP4) untuk pemilu DPR sebanyak 100.000.000 orang pemilih dan dari DP4 ini (misalkan saja, yang menggunakan hak suara/yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara secara benar adalah 70% dari DP4), sehingga suara sah nasional menjadi 70.00.000 suara (pemilih). Berdasarkan data tersebut, bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5% dari suara sah nasional atau sebesar 1.750.000 suara, maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR. Walaupun mereka mempunyai calon terpilih dengan suara terbanyak bahkan dengan jumlah suara melebihi bilangan pembagi pemilih, calon tersebut tetap tidak bisa duduk di parlemen.
Wacana parliamentary threshold secara teoritik itu bagus karena bertujuan untuk memastikan suara yang diperoleh partai politik hasil Pemilihan Umum. Namun, kondisi masyarakat Indonesia yang masih pluralistik dan tingkat kesadaran politik masyarakat yang masih sedang berkembang perlu mendapatkan perhatian yang serius.
Ketentuan tentang parliamentary threshold di masing-masing negara umumnya dipengaruhi oleh keberadaan kultural dan historis negara tersebut berdiri. Tidak ada besaran resmi bagi suatu negara mengenai penerapan parliamentary threshold . Beberapa referensi mengenai parliamentary threshold dibeberapa negara menunjukkan variabel yang berbeda. Negara-negara di dunia yang menerapkan parliamentary threshold , tidak ada batas mutlak bagi setiap negara. Batas mutlak ini tidak membubuhkan adanya suatu keharusan bagi setiap negara untuk menerapkannya. Hal yang lazim ada adalah terdapat pengecualian dari mekanisme parliamentary threshold.
Di Indonesia parliamentary threshold merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk di parlemen. Jadi, setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, lalu dibagi dengan jumlah suara secara nasional. Ketentuan tersebut diterapkan dalam Pemilihan Umum 2009, ketentuan tersebut dirumuskan secara implisit dalam Pasal 202 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah4. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Sedangkan di beberapa negara menerapkan ambang batas penempatan anggota parlemen oleh partai politik sangat bervariasi dimulai dari angka 2% sampai dengan 5% angka angka tersebut tidak dapat di jelaskan dari mana perolehannya yang pasti angka tersebut telah disepakati oleh parlemen yang merupakan perwujudan dari kehendak rakyat. Di Indonesia penetapan angka 2.5% tersebut dinilai oleh beberapa pihak dalam hal ini anggota partai politik adalah inkonstitusional (tidak sesuai dengan konstitusi).
Mereka adalah partai-partai politik peserta Pemilu 2009, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot (PP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), dan Partai Merdeka, serta calon anggota DPR peserta Pemilu 2009 dan anggota Parpol peserta Pemilu 2009.
Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan bahwa Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) inkonstitusional (bertetangan dengan Konstitusi). Dalam Proses persidangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan salah satu dari pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan sebagai legal standing dalam perkara No. 3/PUU-VII/2009 karena tidak menunjukkan bukti kartu keanggotaan partai politiknya.
Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi partai politik baik berbentuk electoral threshold maupun parliamentary threshold . Dalam pertimbanagn putusan tersebut diuraikan “Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang- Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan- pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi,”
Sedangkan Mengenai berapa besarnya angka ambang batas, menurut Mahkamah Konstitusi, adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh MK selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.5 Namun dalam Putusan tersebut diuraikan pula dissenting opinion dari Hakim Konstitusi lain yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai penetapan besaran angka electoral threshold maupun parliamentary threshold.
Menurut pandangan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206 , Pasal207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008 tersebut dalam kenyataannya tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan secara cermat norma-norma, jiwa, dan semangat konstitusi dalam UUD 1945, yang justru harus menjadi sumber legitimasi dari seluruh produk perundangundangan yang dibentuk. Kebijakan yang dianut juga jelas bersifat coba-coba, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggunakan electoral threshold sebagai mekanisme penyederhanaan partai, yang belum sempat diterapkan sebelum kemudian beralih kepada parliamentary threshold dan sejumlah threshold lainnya. Oleh karenanya, tidak dapat juga dielakkan timbulnya kesan yang kuat bahwa kepentingan-kepentingan sesaat sangat berpengaruh pada kebijakan yang dilahirkan, dan tidak diuji secara keras kepada prinsip-prinsip konstitusi, yang seharusnya wajib dipatuhi dan dilindungi serta diwujudkan oleh pembentuk Undang-Undang (obligation to protect, to guarantee and to fulfill).
Ketentuan parliamentary threshold 2,5% (dua komalima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, sungguh-sungguh mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakanoleh rakyat pemilih untuk memilih wakilnya di DPR, akan tetapi tidak dijadikan tolok ukur untuk DPRD. Hal demikian dilakukan dengan dalih untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang berada di DPR sebagai salah satu strategi penguatan sistem presidensiil.