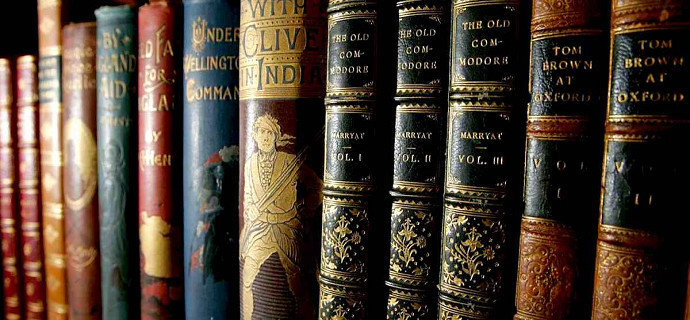
Bagaimana pendapatmu tentang perkembangan novel di Indonesia ?
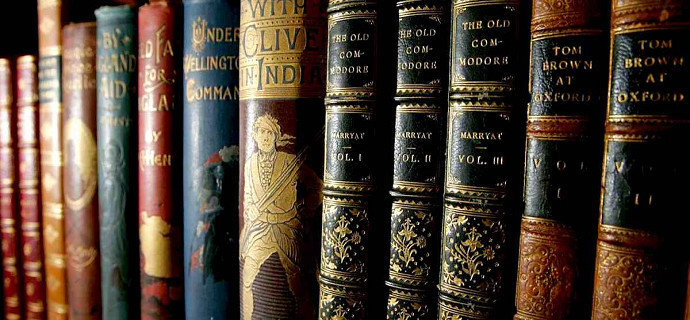
Bagaimana pendapatmu tentang perkembangan novel di Indonesia ?
Dalam perkembangan sastra fiksi Indonesia, dikenal adanya novel mutakhir. Novel Indonesia berkembang pesat sejak dekade 1970-an karena didukung oleh beberapa faktor yakni:
Penggunaan istilah ‘novel Indonesia mutakhir’ bukan periode atau angkatan 1970-an atau Angkatan 2000 dimaksudkan untuk menghindari polemik mengenai lahirnya angkatan sastra dalam dunia sastra Indonesia yang sering menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Sejak Angkatan '66 yang dicetuskan oleh Jassin hingga 1990-an, sastra Indonesia seolah-olah mengalami stagnasi, karena tidak ada angkatan sastra baru. Padahal realitasnya ada banyak karya sastra yang terbit pada dekade 1970-an hingga 1990-an yang memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan Angkatan '66. Baru pada tahun 2000 muncul Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia (2000) yang dikemukakan oleh Korrie Layun Rampan.
Setelah Angkatan '66 sebenarnya telah muncul gagasan lahirnya angkatan sastra baru. Mula-mula Dami N. Toda menyampaikan gagasan lahirnya Angkatan '70 lewat makalahnya “Peta Perpuisian Indonesia dalam Sketsa” (1977), kemudian Sutardji C. Bachri lewat tulisannya “Chairil Anwar, Angkatan '70, dan Kredo Puisi Saya” (1984), Abdulhadi W. M. dengan tulisannya “Angkatan '70 dalam Sastra Indonesia” (1984), dan Korri Layun Rampan dalam makalahnya “Angkatan '80 dalam Sastra Indonesia” (1984). Namun, gagasan mengenai Angkatan '70 dan Angkatan '80 ini seakan-akan terhapus dari sejarah sastra Indonesia, terutama karena tidak didukung oleh antologi karya-karya yang memper- lihatkan ciri dan karakteristik angkatan sastra tersebut (Korrie Layun Rampan, 2000). Baru setelah Rampan menulis antologi Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia (2000), bergulirlah ‘Angkatan 2000’. Itu pun Ahmad Tohari, yang mulai dikenal lewat karya-karyanya sejak akhir 1970-an, tidak termasuk di dalamnya. Adapun karya-karya sastrawan yang terhimpun dalam antologi ini banyak yang sudah mulai muncul sejak dekade 1980-an hingga akhir 1990-an (lihat Korrie Layun Rampan, 2000).
Mencermati realitas itulah maka pengertian novel Indonesia mutakhir di sini lebih mengacu pada pandangan Budi Darma (dalam Aminuddin, 1990), bahwa banyak faktor di luar sastra yang ikut menentukan sastra, termasuk angkatan sastra. Gejala-gejala dalam sastra yang membentuk sastra Indonesia mutakhir menurut Budi Darma menyangkut filsafat, kerinduan arkitipal dan sofistikasi dalam karya sastra.
Filsafat dan sastra kadang-kadang menjadi satu. Filsafat dapat diucapkan lewat sastra, sementara sastra itu sendiri sekaligus dapat bertindak sebagai filsafat. Salah satu aliran filsafat yang muncul dalam sastra Indonesia pada beberapa dekade terakhir adalah eksistensialisme yang derivasinya meliputi allienisme (yang menyiratkan kesendirian atau keterasingan) dan absurdisme (yang menyiratkan bahwa kehidupan kita tidak mempunyai makna) (Budi Darma dalam Aminuddin, 1990). Perkembangan absurdisme dalam sastra menjadi bermacam-macam, antara lain berbentuk karya sastra antilogika, antiplot dan antiperwatakan. Allienisme dan absurdisme terlihat antara lain dalam karya-karya Iwan Simatupang, Kuntowijoyo dan Danarto.
Kerinduan arkitipal (arktipe) menyaran pada adanya kecenderungan para sastrawan yang berusaha menggali kembali akar tradisi subkebudayaan. Bangsa Indonesia yang heterogen berpijak pada dua dunia yang saling menunjang yakni subkebudayaan masing- masing di satu pihak dan kebudayaan Indonesia di pihak lain. Sadar atau tidak kita pasti dilanda kerinduan arkitipal, yakni rindu terhadap sub-subkebudayaan (budaya lokal) masing-masing. Karya- karya Y.B. Mangunwijaya seperti novel Burung-burung Manyar (1981), Burung-burung Rantau (1984), dan Genduk Duku (1986), Umar Kayam dalam Sri Sumarah dan Bawuk (1975), novel Para Priyayi (1992) Ahmad Tohari dalam novel Kubah (1980), trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (1982, 1985, 1986), kumpulan cerpen Senyum Karyamin (1989), Bekisar Merah (1993), dan A.A. Navis dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami (1969), novel Kemarau (1971), menyiratkan arkitipal itu.
Munculnya sastra sufi dengan dimensi transendentalnya juga merupakan pengejawantahan kerinduan arkitipal. Agama dan keyakinan terhadap Tuhan juga subkebudayaan. Hakikat kerinduan arkitipal adalah kerinduan terhadap sebuah subkebudayaan yang telah membentuk kita menjadi manusia Indonesia. Sufisme beserta transendentalnya juga telah membentuk sebagian wajah manusia Indonesia (Budi Darma, dalam Aminuddin, 1990). Karya sastra yang mengandung muatan sufisme, misalnya Khutbah di Atas Bukit (1976) karya Kuntowijoyo, Godlob (1974), Adam Ma’rifat (1982), dan Berhala (1991) karya Danarto.
Sastra bermuatan sejarah juga merupakan pengejawantahan dari arkitipal. Sejarah berdimensi nostalgia, sedangkan nostalgia dapat menjadi saudara kembar kerinduan arkitipal (Budi Darma dalam Aminuddin (Ed), 1990). Banyak sastra Indonesia yang mengangkat masalah sejarah, misalnya karya-karya Y.B. Mangunwijaya : Burung-burung Manyar (1981), dan Genduk Duku (1986), juga Kubah (1980), trilogi Ronggeng Dukuh Paruk (1982) karya Ahmad Tohari; lalu Keberangkatan (1977) karya Nh. Dini dan Anak Tanah Air (1985) karya Ajip Rosidi.
Adapun sofistikasi menyaran pada pandangan pemikiran baru yang mengkristal dalam filsafat. Sebuah pandangan dapat dirumuskan jika memenuhi prasyarat tertentu, antara lain pandangan itu harus mendasar. Biasanya, pandangan yang mendasar dapat lahir karena adanya suatu krisis besar (Budi Darma dalam Aminuddin (Ed.), 1990).
Menurut Budi Darma, setelah lahirnya eksistensialisme, perkembangan dunia pemikiran lebih bersifat evolusioner. Dalam proses evolusioner itu para pemikir bersifat evolusioner pula, yang juga terjadi dalam sastra. Kosongnya filsafat, yakni filsafat yang memadu sastra seperti eksistensialisme tentu saja tidak identik dengan kosongnya perilaku dan kebudayaan. Sastra tetap membawakan pemikiran, meskipun belum tentu pemikiran itu telah dirumuskan menjadi filsafat.
St. Takdir Alisyahbana (STA) selalu memperjuangkan nilai- nilai tertentu yang sudah dirumuskan sendiri sebelumnya. Misalnya, sastra harus membawakan gagasan besar, harus merombak dan harus membawa modernisasi. Satrawan Indonesia yang lain sebenarnya juga membawa gagasan baru, hanya saja mungkin tidak sehebat STA yang muncul sejak masa sebelum kemerdekaan hingga zaman modern. Iwan Simatupang, Ahmad Tohari, Danarto, Kuntowijoyo, dan Ayu Utami dapat dikatakan juga mengusung gagasan-gagasan baru yang cukup mendasar dalam karyanya.