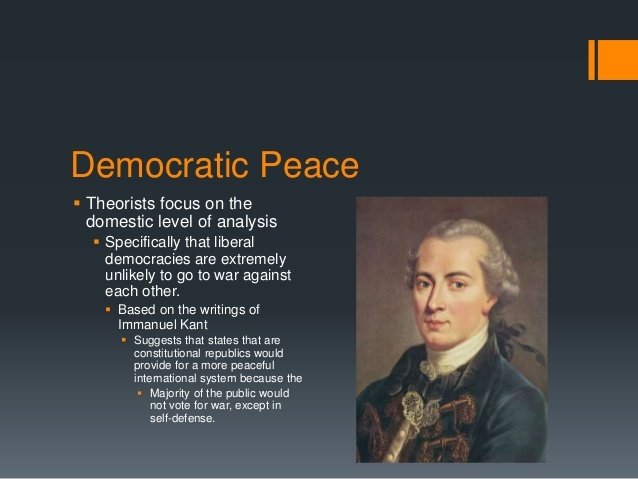
Secara umum, para akademisi yang mendukung teori democratic peace dapat dibagi menjadi dua, yaitu aliran normatif dan struktural. Sedangkan pada masa pasca Perang Dingin, teori Democratic Peace berkembang menuju arah konstruktivisme. Negara-negara demokrasi mengkonstruksi sendiri identitas mereka sebagai negara demokrasi, dan mengkonstruksi identitas negara-negara lain, apakah negara tersebut merupakan negara demokrasi atau tidak. Negara-negara demokrasi akan cenderung bersikap lebih damai dengan negara- negara lain yang mereka anggap memiliki identitas yang sama dengan mereka, yaitu identitas demokrasi. Konstruksi identitas dapat dibentuk oleh perilaku negara secara internal dan eksternal, maupun hal-hal lain seperti sejarah hubungan kedua negara. Nilai dan norma demokrasi pasca Perang Dingin cenderung lebih bersifat praktis, sehingga identitas mempengaruhi interaksi negara terhadap negara lainnya. Apabila sebuah negara menganggap negara lain memiliki identitas yang berbeda, yaitu non- demokrasi, maka tetap terdapat kemungkinan terjadinya perang apabila mereka saling terlibat konflik (Doyle, 1983).
Pendukung aliran normatif percaya bahwa negara-negara demokrasi bersifat lebih damai karena memiliki norma dan nilai anti-kekerasan. Sedangkan pendukung aliran struktural percaya bahwa struktur negara demokrasi menghambat mereka untuk melakukan perang. Sesungguhnya landasan normatif dan struktural saling melengkapi, karena norma dan nilai demokrasi mempengaruhi struktur demokrasi, dan demikian pula sebaliknya. Menurut John Owen dan Michael Doyle, norma dan nilai anti kekerasan yang dimiliki negara-negara demokrasi berasal dari ide-ide liberal ( liberal ideas ), seperti kesetaraan di depan hukum, kebebasan individu, dll, mempengaruhi institusi demokrasi (membuka cara-cara non-kekerasan untuk menyelsaikan konflik), dan ideologi demokrasi (demokrasi tidak saling berperang), sehingga mencegah perilaku agresif negara, dan menciptakan democratic peace. Namun demikian, Michael Doyle melihat warisan ide-ide liberal tidak menghasilkan perdamaian yang seutuhnya, melainkan menghasilkan “ separate peace ”, karena tidak tertutup kemungkinan negara demokrasi berperang dengan negara non-demokrasi.16 Walaupun demikian, Doyle melihat saat ini terjadi peningkatan jumlah negara liberal, sehingga separate peace menjadi semakin signifikan dan mendorong terjadinya world peace (Doyle, 1983).
Penjelasan mengenai aliran normatif democratic peace dapat pula dilihat dari tulisan Bruce Russet yang berjudul “ Grasping the Democratic Peace ”. Di dalam tulisannya tersebut, Bruce Russet membagi pembahasannya mengenai teori democratic peace ke dalam tiga periode waktu, yaitu abad ke-19, ke-20, dan abad ke-21. Menurut Bruce Russet, baru pada abad ke-21 negara demokrasi enggan berperang karena memiliki norma-norma anti-kekerasan. Sedangkan pada abad ke-20 demokrasi tidak saling berperang lebih karena memiliki musuh bersama, dan pada abad ke-19 karena jumlahnya sedikit dan terdapat lack of proximity.
Di dalam pembahasannya, Russett mengutip pendapat Immanuel Kant mengenai konsep perpetual peace , di mana demokrasi atau republican constitution merupakan salah satu elemen dari perdamaian yang berkelanjutan. Russett juga mengamati bahwa Woodrow Wilson menggunakan kerangka teori democratic peace dalam menyusun Wilson’s Fouteem Foints. Di dalam Wilson’s Fourteen Points, terdapat elemen “ cosmopolitan law ” dan “ pacific union ” seperti yang telah dijelaskan Kant. Poin ketiga dalam Wilson’s Fourteen Points meminta setiap negara untuk menghilangkan semua economic barriers dan menciptakan kondisi perdagangan yang setara di antara negara-negara di dunia. Poin keempatbelas meminta negara-negara dunia untuk membentuk sebuah asosiasi di tingkat internasional yang dibentuk berlandaskan sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menciptakan pengakuan bersama terhadap ketergantungan politik dan integritas territorial, baik kepada negara-negara besar maupun negara-negara kecil.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bruce Russet menggambarkan perkembangan teori democratic peace dari abad ke-19 hingga abad ke-21, Pada abad ke-19, negara-negara demokrasi tidak saling berperang karena tiga hal, yaitu:
- jumlah mereka yang sedikit;
- lack of proximity atau jarak mereka yang berjauhan; dan
- kurangnya power negara-negara demokrasi pada saat itu.
Power merupakan elemen yang sangat penting untuk terjadinya sebuah perang. Negara-negara cenderung berperang ketika mereka berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menang, yang berarti bahwa setidaknya mereka memiliki power untuk melakukan penetrasi terhadap wilayah negara lainnya.
Pada abad ke-20, negara-negara demokrasi tidak saling berperang karena mereka memiliki musuh bersama (common enemy), yaitu Blok Timur yang berisi negara-negara sosialis-komunis. Selama adab ke-20, khususnya selama perang dingin, demokrasi merupakan sebuah ideologi yang menyatukan negara-negara Blok Barat untuk menghadapi negara-negara Blok Timur. Pendapat yang sama diutarakan oleh James Lee Ray. Menurut Ray, teori Democratic Peace merupakan sebuah fenomena yang terbentuk akibat Perang Dingin. Pasca Perang Dunia kedua, negara-negara demokrasi memiliki sebuah musuh dan ancaman bersama, yaitu Blok Timur, yang mendorong mereka untuk bersatu dan bekerja sama untuk melawan Uni Soviet dan sekutunya. Hal yang sama tidak terlihat di Blok Timur. Walaupun mereka memiliki musuh bersama, yaitu blok Barat, negara-negara Blok Timur tetap saling terlibat perang. Uni Soviet menginvasi Hungaria, Ceko, dan Afghanistan; Vietnam menyerang Kamboja; dan Cina menyerang Vietnam (Ray, 2001). Kebiasaan negara-negara demokrasi untuk tidak saling berperang pada masa perang dingin berlanjut hingga pasca perang dingin, didukung pula dengan bertambahnya jumlah negara demokrasi.
Pada abad ke-21, negara-negara demokrasi tidak saling berperang karena nilai-nilai dan norma perdamaian yang mereka miliki, dan praktik resolusi konflik yang damai yang mereka terbiasa lakukan. Negara-negara demokrasi memiliki pemilihan umum bagi rakyat untuk memilih representasi mereka di parlemen, dan memiliki pemisahan kekuasaan di pemerintah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Proses check and balances di antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik di dalam sistem pemerintahan demokrasi. Hal tersebut mendorong terjadinya kerjasama dan resolusi konflik yang damai seperti yang dijelaskan sebelumnya. Masyarakat, yang biasanya menjadi korban perang, dapat mendorong wakil mereka di parlemen untuk membuat kebijakan-kebijkan yang anti- perang, seperti membuka kerjasama ekonomi, sehingga perang semakin sulit terjadi di negara-negara demokrasi. Pemerintah di negara demokrasi memiliki insentif lebih untuk mendengarkan opini dan kepentingan masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah tidak ingin kehilangan dukungan dari konstituennya yang dapat berujung kepada suara pemilih ( votes ) yang berkurang untuk mereka dan partai mereka di pemilihan umum berikutnya.
Pendapat yang serupa diutarakan oleh Thomas Risse. Risse menggunakan landasan normatif melalui pendekatan social-constructivist-perspective . Riise berpendapat bahwa demokrasi mengkonstruksi teman dan musuhnya sendiri, dengan mengacu kepada motif struktur domestik negara lain (agresif atau defensif). Negara demokrasi menganggap negara demokrasi lainnya pacific karena menggunakan norma-norma demokrasi secara internal, dan berekspektasi bahwa negara tersebut akan menggunakannya secara eksternal. Demokrasi curiga bahwa non-demokrasi memiliki intensi agresif, karena melihat perilaku domestik mereka yang tidak demokratis, dan khawatir perilaku tersebut tetap dilakukan secara eksternal. Oleh sebab itu, pembentukan “ pacific union ” seperti EU di antara negara-negara demokrasi mudah dilakukan, namun hal yang sama sulit dilakukan dengan non-demokrasi, karena demokrasi berasumsi bahwa non-demokrasi akan bersikap agresif dan mencari relative-gains dari kerjasama mereka.24
Bueno de Mesquita dkk, lebih cenderung menggunakan landasan struktural dalam penjelasannya mengenai teori democratic peace . Menurut Buena de Mesquita dkk, negara demokrasi memakan waktu yang lebih singkat untuk menyelesaikan konflik, ketimbang negara non-demokrasi. Selain itu, negara demokrasi memiliki potensi yang lebih kecil untuk melakukan perang dalam menyelesaikan sebuah masalah, dibandingkan negara non-demokrasi. Di dalam tulisannya yang berjudul, “ An Institutional Explanation of the Democratic Peace ”, Bueno de Mesquita dkk memiliki dua alasan mengapa negara demokrasi enggan berperang. (a) Pemimpin demokrasi perlu mendapatkan dukungan dari konstituennya untuk membuat sebuah kebijakan, dan konstituen cenderung enggan mendukung kebijakan untuk berperang, Pemimpin demokrasi berusaha untuk mengikuti keinginan konstituennya untuk tidak berperang, agar tidak kehilangan konstituen dan dapat tetap mempertahankan kekuasaannya (Mesquita, 1999).
Selain itu, proses perumusan kebijakan di negara demokrasi memerlukan waktu yang lama, karena membutuhkan persetujuan mayoritas parlemen. Oleh sebab itu, kebijakan untuk berperang memerlukan waktu yang lama untuk disahkan, sehingga memungkinakan negara untuk melakukan negosiasi dan diplomasi selama selang waktu tersebut. Bentuk institusi dan norma yang dianut oleh negara demokrasi dapat sedemikian rupa membuat negara demokrasi menjadi lebih pacific ketimbang negara non-demokrasi.
Bueno de Mesquita dkk percaya bahwa negara demokrasi membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk menyelesaikan konflik ketimbang negara non- demokrasi. Bueno de Mesquito dkk menjelaskan bahwa penyebab konflik yang berlarut-larut adalah elemen ketidakpastian ( uncertainty ). Ketika dalam konflik terdapat kepastian tentang siapa yang bakal menang dan kalah (misalnya melalui perhitungan kapabilitas militer), maka negara yang lebih lemah akan memilih untuk melakukan negosiasi, dan negara yang kuat akan menerimanya, karena negosiasi lebih less-costly ketimbang perang. Bueno de Mesquita dkk menyebutkan bahwa konflik di antara negara-negara demokrasi memakan waktu yang relatif lebih singkat ketimbang konflik dengan negara non-demokrasi. Negara demokrasi lebih selektif untuk membuat kebijakan perang, sehingga akan memastikan terlebih dahulu outcome dari perang. Negara demokrasi, jika terpaksa, hanya akan terlibat ke dalam perang yang mereka yakin akan meraih kemenangan. Kekalahan dalam perang kemungkinan besar akan menjadi akhir karir pemimpin di negara demokrasi. Namun sesungguhnya apapun prediksi outcome dari perang, negara demokrasi akan memilih negosiasi karena cenderung paling less-costly . Sementara negara otoriter tidak selektif dalam membuat kebjakan perang. Mereka dapat membuat kebijakan perang kapanpun sesuai dengan kehendak pemimpinnya, sehingga konflik lebih lama berlangsung.
Pendukung landasan struktural lainnya adalah Michael Tomz. Menurut Tomz, Pemimpin negara demokrasi dihambat ( restrain ) untuk berperang karena ingin tetap mempertahankan dukungan konstituennya ( public ), yang cenderung enggan berperang, karena cost -nya yang besar. Menurut penelitian Michael Tomz, terdapat dua alasan mengapa negara-negara demokrasi enggan saling berkonflik. Secara empiris, para pemimpin di negara-negara demokrasi enggan berkonflik atau berperang karena mereka takut kehilangan suara konstituen ( voters ). Masyarakat di negara-negara demokrasi melihat bahwa konflik dan perang merupakan sesuatu yang mahal ( costly ), sehingga mereka akan memilih pemimpin yang tidak menginginkan perang. Secara normatif, Michael Tomz, menemukan bahwa negara-negara demokrasi tidak mau saling berperang karena tidak mau merusak hubungan diplomatik yang mereka miliki. Institusi demokrasi seperti itulah yang membuat negara demokrasi menjadi lebih damai, dan mendorong terjadinya Democratic Peace.