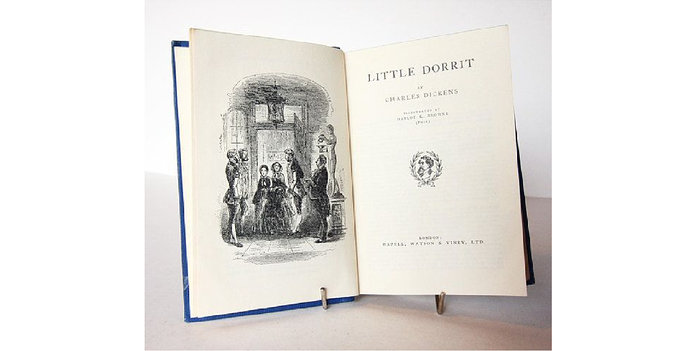Tidak ada sebuah teks pun yang benar-benar mandiri, dalam arti bebas dari pengaruh teks lain, tanpa ada latar belakang sosial budaya sebelumnya. Berdasarkan kenyataan itu, untuk mengungkapkan makna sebuah karya sastra diperlukan pengetahuan mengenai kebudayaan yang melatarbelakangi karya sastra tersebut (Teeuw, 1984).
Prinsip intertektualitas pertama kali dikembangkan oleh Julia Kristeva dari Perancis. Prinsip tersebut menganggap bahwa setiap teks sastra harus dibaca dengan latar belakang teks-teks lainnya. Sejalan dengan itu, Teeuw (2003), menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada sebuah teks yang sungguh-sungguh mandiri. Menurut Teeuw (2003), penciptaan sastra dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, karena kerangka pemahaman teks baru memerlukan latar belakang pengetahuan tentang teks-teks yang telah mendahuluinya. Hutcheon (dalam Ratna, 2004), juga menegaskan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada teks tanpa interteks, dan interteks memungkinkan adanya teks plural. Sebab itu interteks merupakan indikator utama untuk melihat adanya pluralisme budaya.
Teori Interteks memandang setiap teks sastra perlu dibaca dengan latar belakang teks-teks lain, dalam arti bahwa penciptaan dan pembacaan sastra tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai acuan. Hal itu tidak berarti bahwa teks baru hanya mengambil teks-teks sebelumnya sebagai acuan, tetapi juga menyimpangi dan mentransformasikannya dalam teks-teks yang dicipta kemudian (Teeuw, 1984).
Kristeva (1980) menyatakan, bahwa intertekstual adalah masuknya teks lain ke dalam suatu teks, saling menyilang dan menetralisasi satu dengan lainnya (bdk. Hawkes, 1978; Culler, 1981; Junus, 1985). Setiap teks merupakan mosaik kutipan- kutipan, penyerapan, dan transformasi teks-teks lain (dalam Culler, 1975). Setiap karya sastra tidak lahir dalam keadaan kosong, ia merupakan arus kesinambungan tradisi sepanjang masa (Mukarovsky dalam Burbank, 1978). Karenanya, pemahaman maknanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melatari sosiobudaya pengarang dan juga pembacanya (bdk. Chamamah-Soeratno, 1991). Karya sastra merupakan aktualisasi dari sebuah sistem konvensi atau kode sastra dan budaya, dan merupakan pelaksanaan pola harapan pada pembaca yang ditimbulkan dan ditentukan oleh sistem kode dan konvensi itu (Teeuw, 1980).
Hubungan intertekstualitas adalah hubungan antarkarya dan juga penandaan partisipasinya dalam lingkup diskursif budaya. Kajian interteks lebih jauh daripada hanya menelusuri pengaruh-pengaruh; ia meliputi praktik-praktik diskursif yang anonim, mengkodekan asal usul yang hilang sehingga memungkinkan tindak penandaan teks-teks yang kemudian (Culler, 1981). Prinsip intertekstualitas bukan hanya masalah pengaruh atau saduran atau penjiplakan.
Bagi Kristeva (dalam Junus, 1985) kehadiran teks dalam teks lain melibatkan suatu proses pemahaman dan pemaknaan (signifying process). Perspektif intertekstualitas, kutipan-kutipan yang membangun teks adalah anonim, tak terjajaki, walaupun demikian sudah dibaca; kutipan-kutipan tersebut berfungsi sebagai (yang) sudah dibaca (Barthes dalam Culler, 1981). Sejalan dengan pandangan Kristeva, bahwa intertekstualitas adalah himpunan pengetahuan yang memungkinkan teks bermakna; makna suatu teks bergantung kepada teks-teks lain yang diserap dan ditransformasinya (dalam Culler, 1981).
Pendekatan interteks secara kongkret dilakukan dengan baik oleh Riffaterre (1978) terhadap puisi Perancis. Riffaterre berkesimpulan, bahwa puisi Perancis akan dapat dipahami dengan baik jika kita membaca latar belakang puisi-puisi sebelumnya. Artinya, sebuah karya sastra akan mendapat makna penuh dalam hubungannya dengan karya lain yang mendahuluinya. Riffaterre menyebutnya dengan hipogram, yakni tulisan yang menjadi dasar penciptaan karya lain yang lahir kemudian, sering kali secara kontrastif, dengan memutarbalikkan esensi, amanat karya sebelumnya.
Teeuw (1983) menyatakan, bahwa hipogram itu barangkali mirip dengan bahasa Jawa latar. Karya yang diciptakan berdasarkan hipogram itu disebut sebagai karya transformasi karena mentransformasikan hipogram itu. Di sinilah tampak titik temu pandangan Teeuw dengan Barthes, bahwa teks dibangun atas kutipan- kutipan yang anonim, namun sudah dibaca.
Junus (1985) merumuskan hubungan intertekstualitas dalam beberapa wujud:
-
Teks yang dimasukkan itu mungkin teks yang kongkret, atau mungkin teks yang abstrak. Yang penting adalah kehadiran sifatnya
-
Kehadiran suatu teks tertentu dalam teks lain secara fisikal; ada petunjuk ke arah hal itu, walaupun hanya disadari oleh pembaca-pembaca tertentu
-
Penggunaan nama tokoh yang sama
-
Kehadiran unsur dari suatu teks dalam teks lain; jadi lebih terbatas
-
Kehadiran kebiasaan berbahasa tertentu dalam suatu teks. Keadaan ini tidak dapat dihindarkan, mungkin karena tradisi yang mendasari suatu genre
-
Yang hadir mungkin teks kata-kata, yaitu kata atau kata-kata atau paling tidak ambigu maknanya.
Atas dasar kemungkinan-kemungkinan yang menunjukkan adanya unsur-unsur intertekstualitas tersebut, makin jelaslah bahwa keberadaan suatu teks tidak dapat dilepaskan dari teks-teks lain. Hubungan intertekstualitas, mungkin merujuk pada teks bahasa atau teks bukan bahasa. Prinsip intertekstualitas membawa kita utuk memandang teks-teks terdahulu sebagai sumbangan pada suatu kode yang memungkinkan efek signification, pemaknaan yang bermacam-macam. Dengan demikian intertekstualitas tidak hanya penting dalam usaha memberi interpretasi tertentu terhadap karya sastra. Lebih dari itu intertekstualitas memainkan peran sangat penting dalam semiotik sastra.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pendekatan intertekstualitas merupakan pendekatan dalam menganalisis karya sastra yang bertujuan untuk menemukan hubungan yang bermakna antara dua teks atau lebih. Pemahaman sastra intertekstualitas hakikatnya bertujuan untuk menggali secara maksimal makna yang terkandung dalam teks dengan melihat hubungannya dengan teks lain.