
Apa yang dimaksud dengan tasawuf suni dalam Islam?

Apa yang dimaksud dengan tasawuf suni dalam Islam?

Tasawuf sunni merupakan tasawuf yang pengikut-pengikutnya memagari dengan Al-Quran dan sunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohaniah mereka dengan keduanya.
Tasawuf Sunni merupakan tasawuf yang mempunyai karakter dinamis karena selalu mendahulukan syariat. Seseorang tidak akan mencapai haqiqah apabila tidak melalui syari’ah, sedangkan proses pencapaian haqiqah harus melalui maqamat (terminal-terminal).
Ciri-ciri tasawuf Sunni antara lain sebagai berikut.
Melandasakan diri pada Al-Quran dan Sunnah.
Tasawuf jenis ini dalam pengejawantahan ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Al-Quran dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Mereka tidak mau menerjunkan paham yang berada di luar pembahasan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang mereka pahami, kalaupun harus ada penafsiran sifatnya hanya sekadarnya dan tidak begitu mendalam.
Tidak menggunakan terminologi-terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syatahat.
Terminologi tersebut dikembangkan tasawuf Sunni secara lebih transparan, sehingga tidak kerap bergelut dengan term-term syatahat. Kalaupun ada term yang mirip syatahat, itu dianggapnya sebagai pengalaman pribadi dan mereka tidak menyebarkannya kepada orang lain. Pengalaman yang ditemukan itu, mereka anggap pula sebagai sebuah karamah atau keajaiban. Sejalan dengan itu, Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip At-Taftazani, memuji para pengikut Al-Qusyairi yang beraliran Sunni, karena dalam aspek ini mereka memang meneladani para sahabat. Pada diri para sahabat dan tokoh angkatan salaf telah banyak terjadi kekeramatan seperti ini.
Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia.
Dualisme yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan, dalam hal esensinya, hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda di antara keduanya. Sedekat apa pun manusia dengan Tuhannya, tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Al-Quran dan hadis dengan jelas menyebutkan bahwa “ inti” makhluk adalah “bentuk lain” dari Allah. Hubungan antara Sang Pencipta dan yang diciptakan bukanlah salah satu persamaan, tetapi “bentuk lain”. Benda yang diciptakan adalah bentuk lain dari penciptaan-Nya.
Kesinambungan antara haqiqah dan syari’ah.
Dalam pengertian lebih khusus, keterkaitan antara tasawuf (sebagai aspek batiniahnya) dengan fiqh (sebagai aspek lahirnya). Hal ini merupakan konsekuensi dari paham di atas. Karena berbeda dengan Tuhan, dalam berkomunikasi dengan-Nya manusia tetap pada posisi atau kedudukannya sebagai objek penerima informasi dari Tuhan. Kaum sufi dari kalangan Sunni tetap memandang penting persoalan-persoalan lahiriah-formal, seperti aturan yang dianut fuqaha. Aturan-aturan itu bahkan sering dianggap sebagai jembatan untuk berkomukasi dengan Tuhan.
Lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, serta pengobatan jiwa dengan cara riyadhah (latihan mental) dan langkah takhali, tahalli, dan tajalli.
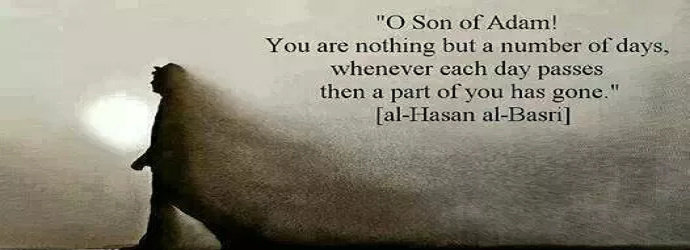
Hasan Al-Bashri adalah seorang sufi angkatan tabi’in, seorang yang sangat taqwa, wara’ dan zahid. Nama lengkpanya ialah Abu Sa’id al-Hasan ibn Abi al- Hasan. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 H tetapi dibesarkan di Wadi al-Qura. Setahun setelah perang Shiffin dia pindah ke Bashrah dan menetap di sana sampai ia meninggal tahun 110 H. setelah ia menjadi warga Bashrah.
Ia membuka pengajian di sana karena keprihatinanya melihat gaya hidup dan kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi sebagai salah satu ekses dari kemakmuran ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa itu. Gerakan itulah yang menyebabkan Hasan Basri kelak menjadi orang yang sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di Bashrah. Di antara ajarannya yang terpenting adalah al-zuhd serta al-khauf dan raja’.
Dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhd terhadap kehidupan duniawi sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Hasan Al-Basri mengumpamakan dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan tetapi racunnya dapat mematikan. Oleh karen aitu dunia itu harus dijauhi dan kemegahan serta kenikmatan hidup duniawi harus ditolak.
Prinsip kedua ajaran Hasan al-Basri adalah Khauf dan raja’, dengan pengertian merasa takut kepada siksa Allah karena berbuat dosa dan sering melalaikan perintah Allah. Menyadari kekurang sempurnaannya dalam mengabdi kepada Allah, timbullah rasa was-was dan takut, khawatir mendapatmurka dari Allah. Dengan adanya rasa takut itu pula menjadi motivasi bagi seseornag untuk mempertinggi kualitas dan kadar pengabdiannnya kepada Allah dengan sikap raja’ atau pengharapan akan ampunan dan karunianya.
Oleh karena itu prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakuka mawas diri atau muhasabah agar selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Dengan sikap itu pula, seseorang akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan segala macam perbuatan yang tidak baik. Menurut faham ini, bahwa orang beriman berada dalam keadaan ketakutan dan kecemasan disebabkan dua hal, yaitu karena dosa yang telah lalu, ia tidak tahu persis apa yang akan menimpa dirinya karena dosanya itu, dan kedua karena usai yang tersisa, ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa.
Orang yang menyadari, bahwa mati itu adalah sesuatu yang pasti dan kiamat itu tempat ditunaikan janji serta berdiri di hadapan Allah adalah sesuatu yang pasti akan dialami, pastilah ketakutan akan selalu berkepanjangan dalam dirinya dan dalam pengabdiannya. Pandangan dan sikap Hasan al-Basri yang demikian itu benar-benar terlihat dalam kehidupannya sehari-hari, karena kuatnya perasaan takut dalam dirinya, ia menganggap neraka diciptakan hanya untuk dirinya sendiri.
Hasan al-Basri berkeyakinan, bahwa perasaan takut atau khauf itu sama dengan memetik amal saleh. Katanya, tidak seorang manusiapun pada kurun yang pertama yang tidak merasa takut dan keluh kesah. Demi Allah, wahai anak Adam, jika kamu membaca Al-Quran dan kamu menghayatinya, sesungguhnya kekuatanmu akan berkepanjangan di dunia ini dan rasa takut akan semakin mengikatmu. Segala kesenangan yang bukan surga adalah tidak berarti apa-apa karena ia tidak bernilai. Surga adalah perasaan nikmat karena ridha Allah, sedangkan neraka ialah puncak kegelisahan merasakan murka Allah.
Kesimpulan dari ajaran Hasan al-Basri adalah, zuhd atau menjauhi kehidupan duniawi sehingga perhatian terpusat kepada kehidupan akhirat. Oleh karena itu, selalu mawas diri dan selalu memikirkan kehidupan ukhrawi, adalah jalan yang akan menyampaikan seseorang ke kebahagiaan yang abadi.

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Al-Harits bin Asad Al-Bashri Al- Baghdadi Al-Muhasibi. Tokoh aufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia lahir di Bashrah, Irak, tahun 165 H/781 M. Ia adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapabidang ilmu seperti tasawuf, hadits dan fiqih. Ia merupakan figur sufi yang dikenal senantiasa menjaga dan mawas diri terhadap perbuatan dosa. Ia juga sering kali mengintropeksi diri menurut amal yang dilakukannya. Ia merupakan guru bagi kebanyakan ulama di Baghdad. Orang yang paling banyak menimba ilmu darinya dan yang dipandang sebagai muridnya paling dekat dengannya adalah Al-Junayd Al-Baghdadi (w. 298 H).
Al-Muhasibi menulis sejumlah buku. Menurut Abd Al-Mun’im Al-Hifni, seorang ahli tasawuf dari mesir, Al-Muhasibi menulis kurang lebih 200 buku. Di antara buku-bukunya ialah Ar-Ri’ayah li Huquqillah (Pemeliharaan Terhadap Hak-Hak Allah), Al-Washaya (Wasiat-Wasiat), Al-‘Aql, Al-Makasib (Keberuntungan ), dan Al-Masaa’il fi Amal Al-Qulub wa Al-Jawarih (Berbagai Masalah Mengenai Perbuatan Hati Dan Anggota Badan).
Al-Muhasibi (w.243 H) menempuh jalan tasawuf karena hendak keluar dari keraguan yang dihadapinya. Tatkala mengamati madzhab-madzhab yang dianut umat Islam, Al-Muhasibi menemukan kelompok-kelompok. Di antara mereka ada sekelompok orang yang tahu benar tentang keakhiratan. Namun, jumlah mereka sangat sedikit. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu karena kesombongan dan motivasi keduaniaan. Di antara mereka terdapat pula orang-orang yang terkesan sedang melakukan ibadah karena Allah, tetapi sesungguhnya tidak demikian.
Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui ketaqwaan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, wara’, dan meneladani Rasulullah. Tatkala sudah melaksanakan hal-hal di atas, menurut Al- Muhasibi, seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah berupa penyatuan antara fiqh dan tasawuf. Ia akan meneladani Rasulullah dan lebih mementingkan akhirat dari pada dunia.
Ajaran-Ajaran Tasawuf Al-Muhasibi
Makrifat
Al-Muhasibi berbicara pula tentang makrifat. Untuk itu, ia menulis sebuah buku tentangnya. Namun, dikabarkan bahwa ia tidak diketahui alasannya kemudian membakarnya. Ia sangat berhati-hati dalam menjelaskan batasan- batasan agama, dan tidak sekali-kali mendalami pengertian batin agama yang dapat mengaburkan pengertian lahirnya dan megaburkan keraguan. Inilah yang mendasarinya untuk memuji sekelompok sufi yang tidak berlebih-lebihan dalam menyelami pengertian batin agama. Dalam konteks ini pula ia menuturkan bahwa hadits Nabi,
“Pikirkanlah makhluk-makhluk Allah dan jangan coba-coba memikirkan dzat Allah, sebab kalian akan tersesat karenanya.”
Berdasarkan hadits tersebut Al-Muhasibi mengatakan bahwa makrifat harus ditempuh melalui jalan tasawuf yang mendasar kepada kitab dan sunnah.
Al-Muhasibi menjelaskan tahapan-tahapan makrifat sebagai berikut:
Taat. Awal dari kecintaan kepada Allah adalah taat. Taat merupakan wujud konkret ketaatan hamba kepada Allah. Kecintaan kepada Allah hanya dibuktikan dengan jalan ketaatan, bukan sekedar ungkapan-ungkapan kecintaan semata sebagaimana dilakukan sementara orang mengekspresikan kecintaan kepada Allah hanya dengan ungkapan-ungkapan, tanpa pengamalan merupakan kepalsuan semata. Di antara implementasi kecintaan kepada Allah adalah memenuhi hati dengan sinar. Sinar ini kemudian melimpah pada lidah dan anggota tubuh yang lain.
Aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati merupakan tahap makrifat selanjutnya.
Allah menyingkapkan khazanah-khazanah keilmuan dan kegaiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di atas. Ia akan menyaksikan berbagai rahasia yang selama ini disimpan Allah.
Tahap keempat adalah apa yang dikatakan oleh sementara sufi dengan fana’ yang menyebabkan baqa’.
Khauf Dan Raja’
Dalam pandangan Al-Muhasibi, khauf (rasa takut) dan raja’ (pengharapan) menempati posisi penting dalam perjalanan seseorang membersihkan jiwa. Ia terkesan mengaitkan kedua sifat itu dengan etika-etika keagamaan lainnya, yakni ketika disifati dengan dua sifat di atas, seseorang secara bersamaan disifati pula dengan sifat-sifat lainnya. Pangkal wara’, menurutnya adalah ketakwaan, pangkal ketakwaan adalah introspeksi diri ( muhasabat an-nafs), pangkal introspeksi diri adalah khauf dan raja’, pangkal khauf dan raja’ adalah pengetahuan tentang janji dan ancaman Allah, sedangkan pangkal pengetahuan tentang keduanya adalah perenungan.
Khauf dan raja’ dapat dilakukan dengan sempurna hanya dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Dalam hal ini ia terkesan pula mengaitkan kedua sifat itu dengan ibadah dan dengan janji serta ancaman Allah. Untuk itu, ia menganggap apa yang diungkapkan Ibnu Sina dan Rabi’ah Al-‘Adawiyyah sebagai jenis fana’ atau kecintaan kepada Allah yang berlebih-lebihan dan keluar dari apa yang telah dijelaskan Islam sendiri serta bertentangan dengan apa yang diyakini para sufi dari kalangan ahlusunnah. Al-Muhasibi lebih lanjut mengatakan bahwa Al-Quran jelas berbicara tentang pembalasan (pahala) dan siksaan. Ajakan-ajakan Al-Quran pun sesungguhnya dibangun atas dasar targhib (sugesti) dan tarhib (ancaman).
Raja’ dalam pandangan Al-Muhasibi, seharusnya melahirkan amal shaleh. Tatkala telah melakukan amal shaleh, seseorang berhak mengharap pahala daari Allah. Inilah yang dilakukan oleh mukmin yang sejati dan para sahabat Nabi sebagaimana digambarkan oleh ayat:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 218).

Menurut karya Al-Qusyairi, Ar-Risaalah Al-Qusyairiyyah, akan tampak jelas bagaimana Al-Qusyairi cenderung mengembalikan tasawuf ke atas landasan doktrin Ahlus Sunnah, sebagaimana pernyataannya, “Ketahuilah! Para tokoh aliran ini (maksudnya para sufi) membina prinsip-prinsip tasawuf atas landasan tauhid yang benar, sehingga terpeliharalah doktrin mereka dari penyimpangan, selain itu, mereka lebih dekat dengan tauhid kaum salaf maupun Ahlus Sunnah, yang tidak tertandingi serta mengenal macet. Mereka pun tahu hak yang lama, dan bisa mewujudkan sifat sesuatu yang diadakan dari ketiadaannya. Karena itu, tokoh aliran ini, Al-Junaid mengatakan bahwa tauhid adalah pemisah hal yang lama dengan hal yang baru. Landasan doktrin-doktrin mereka pun didasarkan pada dalil dan bukti yang kuat serta gamblang. Dan seperti dikatakan Abu Muhammad Al-Jariri bahwa barang siapa tidak mendasarkan ilmu tauhid pada salah satu pengokohnya, niscaya membuat tergelincirnya kaki yang tertipu ke dalam jurang kehancurannya.
Secara implisit dalam ungkapan Al-Qusyairi tersebut terkandung penolakan terhadap para sufi syathahi, yang mengucapkan ungkapan-ungkapan penuh kesan terjadinya perpaduan antara sifat-sifat ketuhanan, khususnya sifat terdahulu-Nya, dengan sifat-sifat kemanusiaan, khususnya sifat baharunya. Bahkan, dengan konotasi lain, secara terang-terangan Al-Qusyairi mengkritik mereka,
“mereka menyatakan bahwa mereka telah bebas dari perbudakan berbagai belenggu dan berhasil mencapai realitas-realitas rasa penyatuan dengan Tuhan (wushul).
Lebih jauh lagi, mereka tegak bersama Yang Maha Besar, di mana hukum-hukum-Nya berlaku atas diri mereka, sementara mereka dalam keadaan fana. Allah pun, menurut mereka tidak mencela maupun melarang apa yang mereka nyatakan ataupun lakukan. Dan kepada mereka disingkapkan rahasia-rahasia keesaan, dan setelah fana, mereka pun tetap memperoleh cahaya-cahaya ketuhanan, tempat bergantung segala sesuatu…”
Kesehatan Batin
Selain itu, Al-Qusyairi pun mengecam keras para sufi pada masanya, karena kegemaran mereka mempergunakan pakaian orang-orang miskin, sementara tindakan mereka pada saat yang sama bertentangan dengan pakaian mereka. Ia menekankan bahwa kesehatan batin, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, lebih penting ketimbang pakaian lahiriah. Sebagaimana perkataannya, “Duhai, saudaraku! Janganlah kamu terpesona oleh pakaian lahiriah maupun sebutan yang kau lihat (pada sufi sezamannya). Sebab itu, ketika hakikat realitas- realitas itu tersingkapkan, niscaya nampak keburukan para sufi yang mengada-ada dalam berpakaian, setiap tasawuf yang tidak dibarengi dengan kebersihan maupun penjauhan diri dari maksiat adalah tasawuf palsu serta memberatkan diri, dan setiap yang batin itu bertentangan dengan yang lahir adalah keliru serta bukannya
yang batin, dan setiap tauhid yang tidak dibenarkan Al-Quran maupun As-Sunnah adalah pengingkaran Tuhan dan bukan tauhid, dan setiap pengenalan terhadap Allah (makrifat) yang tidak dibarengi kerendahatian maupun kelurusan jiwa adalah palsu dan bukannya pengenalan terhadap Allah.
Penyimpangan Para Sufi
Dalam konteks yang berbeda, dengan ungkapan yang pedas, Al-Qusyairi mengemukakan suatu penyimpangan lain dari para sufi abad kelima Hijriyah,
“Kebanyakan para sufi yang menempuh jalan kebenaran dari kelompok tersebut telah tiada. Dalam bekas mereka, tidak ada yang tinggal dari kelompok tersebut, kecuali bekas-bekas mereka.”
“zaman telah berakhir bagi jalan ini. Tidak, bahkan jalan ini telah menyimpang dari hakikat realitas. Telah lewat zaman para guru yang menjadi panutan mereka. Tidak banyak lagi generasi muda yang mau mengikuti perjalanan dan kehidupan mereka. Sirnalah kerendahatian dan punahlah sudah kesederhanaan hidup. Ketamakan semakin menggelora dan ikatannya semakin membelit. Hlanglah kehormatan agama dari qalbu. Betapa sedikit orang-orang yang berpegang teguh pada agama. Banyak orang menolak membedakan masalah halal dan haram. Mereka cenderung meninggalkan sikap menghormati orang lain dan membuang jauh rasa malu. Bahkan, mereka menganggap enteng permasalahan ibadah, melecehkan puasa dan sholat, dan terbuai dalam medan kemabukan. Dan mereka jatuh dalam pelukan nafsu syahwat dan tidak peduli sekalipun melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan.”
Pendapat Al-Qusyairi di atas barangkali terlalu berlebihan. Namun, apapun masalahnya, paling tidak hal itu menunjukkan bahwa tasawuf pada masanya mulai menyimpang dari perkembangannya yang pertama, baik dari segi akidah atau dari segi-segi moral dan tingkah laku.
Oleh karena itu pula, Al-Qusyairi menyatakan bahwa ia menulis risalahnya karena dorongan rasa sedihnya melihat apa-apa yang menimpa jalan tasawuf. Ia tidak bermaksud menjelek-jelekkan salah seorang dari kelompok tersebut dengan mendasarkan diri pada penyimpangan sebagian penyerunya. Risalahnya itu, menurutnya, sekadar “pengobat keluhan” atas apa yang menimpa tasawuf pada masanya.
Dari uraian di atas tampak jelas bahwa pengembalian arah tasawuf, menurut Al-Qusyairi, harus dengan merujuknya pada doktrin Ahl as-Sunnaṯ wa al-jamâ’ah, yang dalam hal ini ialah dengan mengikuti para sufi Sunni abad-abad ketiga dan keempat Hijriyah yang sebagaimana diriwayatkannya dalam Ar- Risâlah.
Dalam hal ini, jelaslah bahwa Al-Qusyairi adalah pembuka jalan bagi kedatangan Al-Ghazali, yang berafiliasi pada aliran yang sama, yaitu Al-Asy’ariyyah, yang nanti akan merujuk pada gagasannya itu serta menempuh jalan yang dilalui Al-Muhasibi maupun Al-Junaid, serta melancarkan kritik keras terhadap para sufi yang terkenal dengan ungkapan-ungkapan yang ganjil.
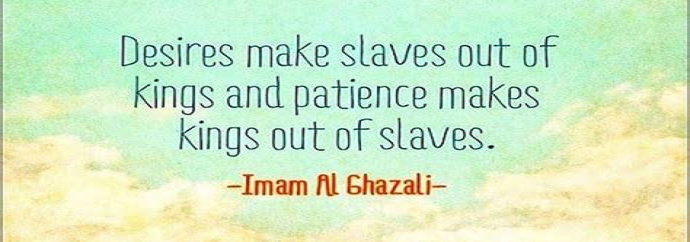
Di dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf Sunni yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi ditambah dengan doktrin Ahlu al-Sunnaṯ wa al- jamâ’aṯ. Dari paham tasawufnya itu, ia menjauhkan semua kecenderungan gnotis yang memengaruhi para filosof Islam, sekte Isma’iliyyah, aliran Syi’ah, Ikhwan Ash-Shafa, dan lain-lainnya. Ia menjauhkan tasawufnya dari paham ketuhanan Aristoteles, seperti emanasi dan penyatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Corak tasawufnya adalah psiko- moral yang mengutamakan pendidikan moral. Hal ini dapat dilihat dalam karya- karyanya seperti Ihyâ’ Ulûm Ad-Din, Minhaj Al-‘Abidin, Mizan Al-Amal, Bidayah Al-Hidayah, Mi’raj As-Salikin, dan Ayuhal Walad.
Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf baru dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa, serta membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah dan berhias dengan selalu mengingat Allah. Ia pun berpendapat bahwa sosok sufi adalah menempuh jalan kepada Allah, dan perjalanan hidup mereka adalah yang terbaik, jalan mereka adalah yang paling benar, dan moral mereka adalah yang paling bersih. Sebab, gerak dan diam mereka, baik lahir maupun batin, diambil dari cahaya kenabian. Selain cahaya kenabian di dunia ini, tidak ada lagi cahaya yang lebih mampu memberi penerangan.
Al-Ghazali menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk berolah rasa dan berolah jiwa, sehingga sampai pada makrifat yang membantu menciptakan (sa’adah).
Makrifat
Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dijelaskan oleh Harun Nasution, makrifat adalah mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. 92 Alat memperoleh makrifat bersandar pada sirr, qalb dan ruh. Selanjutnya, Harun Nasution juga menjelaskan pendapat Al-Ghazali yang dikutip dari Al-Qusyairi bahwa qalb dapat mengetahui hakikat segala yang ada. jika dilimpahi cahaya Tuhan, qalb dapat mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dengan sirr, qalb dan ruh yang telah suci dan kosong, tidak berisi apapun. Saat itulah ketiganya akan menerima iluminasi ( kasyf) dari Allah. Pada waktu itu pulalah Allah menurunkan cahaya-Nya kepada sang sufi sehingga yang dilihat sang sufi hanyalah Allah. Di sini, sampailah ia ke tingkat makrifat.
Di dalam kitab Ihyâ’ Ulûm Ad-Din, Al-Ghazali membedakan jalan pengetahuan sampai kepada Tuhan bagi orang awam, ulama dan orang arif (sufi). Untuk itu, ia membuat perumpamaan tentang keyakinan bahwa si Fulan ada di dalam rumah. Keyakinan orang awam dibangun atas dasar taklid dengan hanya mengikuti perkataan orang bahwa si Fulan ada di rumah, tanpa diselidiki lagi. Bagi ulama’, keyakinan adanya si Fulan di rumah dibangun atas dasar adanya tanda-tanda seperti suaranya yang terdengar walaupun tidak kelihatan orangnya. Adapun orang arif tidak hanya melihat tanda-tandanya melalui suara dibalik dinding. Lebih jauh dari itu, ia pun memasuki rumah dan menyaksikan dengan mata kepalanya bahwa si Fulan benar-benar berada di dalam rumah.
Makrifat seorang sufi tidak dihalangi hijab, sebagaimana ia melihat si Fulan ada di dalam rumah dengan mata kepalanya sendiri. Ringkasnya, makrifat menurut Al-Ghazali tidak seperti makrifat menurut orang awam maupun makrifat ulama mutakallim, tetapi makrifat sufi yang dibangun atas dasar dzauq ruhani dan kasyf ilahi. Makrifat semacam ini dapat dicapai oleh para khawash auliya’ tanpa melalui perantara, langsung dari Allah. Sebagaimana ilmu kenabian yang diperoleh langsung dari Tuhan walaupun dari segi perolehan ilmu ini berbeda antara nabi dan wali. Nabi mendapat ilmu Allah melalui perantara malaikat, sedangkan wali mendapat ilmu melalui ilham. Namun, keduanya sama-sama memperoleh ilmu dari Allah.
As-Sa’adah
Menurut Al-Ghazali, kelzatan dan kebahagiaan yang paling tinggi adalah melihat Allah ( ru’yatullah ). Di dalam kitab Kimiya’ As-Sa’adah, ia menjelaskan bahwa As-Sa’adah (kebahagiaan) itu sesuai dengan watak (tabiat), sedangkan watak sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Nikmatnya mata terletak ketika melihat gambar yang bagus dan indah. Nikmatnya telinga terletak ketika mendengar suara yang merdu. Demikian juga, seluruh anggota tubuh, masing- masing mempunyai kenikmatan tersendiri.
Kenikmatannya qalb sebagai alat untuk memperoleh makrifat, terletak ketika melihat Allah. Melihat Allah merupakan kenikmatan paling agung yang tiada taranya karena makrifat itu sendiri agung dan mulia. Oleh karena itu, kenikmatannya melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sebagaimana perasaan dapat bertemu presiden akan lebih bangga dan senang dari pada perasaan dapat bertemu menteri. Hal ini dapat dianalogikan dengan perasaan kalau dapat berhubungan dengan Allah, Tuhan penguasa alam ini, seseorang tentunya akan lebih senang dan bangga. Inilah kesenangan dan kebahagiaan sejati yang tiada taranya.
Kelezatan dan kenikmatan dunia bergantung pada nafsu dan akan hilang setelah manusia mati, sedangkan kelezatan dan kenikmatan melihat Tuhan bergantung pada qalb dan tidak akan hilang walaupun manusia sudah mati. Sebab qalb tidak ikut mati, malah kenikmatannya bertambah karena dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya terang .
Referensi :