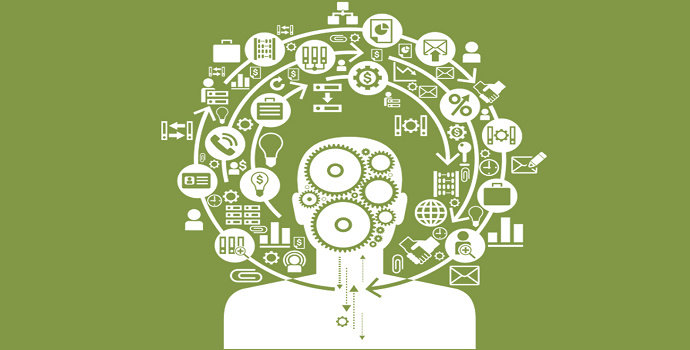Memahami makna ilmu dalam esensinya bukanlah masalah sederhana, melainkan problem filsafat yang justru paling rumit sehingga menimbulkan perbedaan konsep di kalangan pada filosof dalam aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hal ini terlihat sepanjang sejarah sejak zaman Yunani kuno hingga dewasa ini, terdapat beberapa aliran yang mempunyai hukum atau teori sendiri-sendiri untuk melegitimasi dan menunjukkan keunggulannya di atas aliran lain. Oleh karena itu, definisi atau rumusan mengenai ilmu selalu terkait dengan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi pembuatnya.
Al-Munqidz min al-Ḍalāl artinya pembebasan dari kesesatan, yang mengandung maksud, sebuah upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari penyimpangan aqidah warisan dan paham-paham yang tidak sesuai dengan al-Quran dan Hadits.
Mengenai hakikat ilmu secara mutlak, para ulama Islam berbeda pandangan apakah ia bersifat ḍarūrī, a priori, atau naẓarī (inferensial). Di antara definisi-definisi terkuat dari jumhur ulama adalah,
-
Pertama, kelompok mu‘tazilah yang mengatakan bahwa “ilmu adalah meyakini sesuatu sesuai dengan kenyataannya disertai ketenangan dan ketetapan jiwa”;
-
Kedua, al-Bazdawī, yang mendefinikan ilmu sebagai tangkapan objek (al-ma‘lūm) yang sesuai dengan kenyataannya; ketiga, al-Syawkānī (w. 1255 H) yang mengatakan “ilmu adalah sifat yang dengannya apa yang dicari terbuka secara sempurna”.
-
Ketiga, al-Ghazali dalam al-Munqidz, “ilmu adalah tersingkapnya perkara- perkara yang ingin diketahui (al-ma‘lūm) dengan penyingkapan yang sama sekali tidak menyisakan keraguan, tidak diiringi dengan kemungkinan adanya kesalahan, dan terlepas dari pengaruh khayalan dan kebimbangan yang diragukan kebenarannya”.
Di sini perlu ditegaskan, bahwa al-Ghazzālī tidak membedakan antara ‘ilm dengan ma‘rifah seperti dalam tradisi umum kaum sufi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kitabnya, ia sering memakai kedua terma ini dalam arti yang sama.
Bahkan di dalam Rawḍat al-Ṭālibīn, al-Ghazzālī menegaskan bahwa ma‘rifah secara terminologis adalah nama lain bagi ilmu. Menurut al-Ghazzālī, pengonsepsian hakikat ilmu lebih mudah dengan analisis/klasifikasi untuk memperoleh makna formal, dan dengan contoh untuk memperoleh makna esensial. Dengan demikian, hakikat ilmu tidak cukup hanya dengan sesuainya kepercayaan atau pernyataan dengan realitas objek, tetapi juga mengenai ilmu inferensial harus berdasarkan metode ilmiah tertentu yang berpangkal pada skeptik, dan putusan itu merupakan putusan yang pasti.
Sumber dan Klasifikasi Ilmu
Berdasarkan pembentangannya dalam al-Munqidz, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan al-Ghazālī ada tiga sumber ilmu, yaitu pancaindera (al-ḥawās al-khams) berikut daya khayāl dan wahm, akal, dan intuisi (dzawq). Pancaindera bekerja pada di dunianya, yaitu dunia fisis-sensual dan berhenti pada batas kawasan akal. Akal bekerja di kawasan abstrak dengan memanfaatkan input dari pancaindera melalui khayāl dan wahm, dan berhenti pada batas kawasan transendental (tidak terjangkau akal) yang sesudah mengetahui Allah dan rasul-Nya harus diserahkan kepada Rasul atau diperoleh penjelasannya melalui mukāsyafah-musyāhadah.
Secara umum, konsep al-Ghazzālī tentang tiga sumber ilmu ini terlihat bahwa akal teoritis (‘ālimah) merupakan inti hakikat manusia. Namun di satu pihak, ilmu yang terdapat pada akal teoritis itu menimbulkan motif (irādah), yang melalui akal praktis (‘āmilah) membangkitkan potensi-potensi diri (qudrah) untuk melahirkan gerak fisik. Di pihak lain, ilmu muncul dari dua saluran, yaitu saluran luar, yakni wahm dari khayāl dari pancaindera, dan saluran dalam, yakni ilham atau wahyu dari malaikat dari Allah swt. Untuk lebih jelas, ketiga sumber pencapaian ilmu itu akan dibahas satu demi satu.
Pancaindera
Konsep al-Ghazzālī tentang pancaindera sebagai salah satu sumber ilmu, dapat dijelaskan sebagai berikut.
-
Pertama, pancaindera merupakan alat pertama sebagai penangkap objek yang terdapat pada diri manusia, disusul dengan daya khayāl yang menyusun aneka bentuk susunan, dari partikular-partikular yang ditangkap indera, kemudian tamyīz (daya pembeda) yang menangkap sesuatu di atas alam empirik sensual, di sekitar usia tujuh tahun, baru disusul dengan daya akal yang menangkap hukum-hukum akal dan hal-hal lain yang tidak ada pada fase-fase sebelumnya.
Pancaindera lebih menguasai diri manusia, dan pada asal fitrahnya, manusia lebih menerima dan mengikuti konklusi pancaindera dan wahm, karena adanya lebih dahulu dari akal, yang dianggap pendatang baru dan terus-terusan ditolak sampai ia mempunyai posisi yang kuat dan dapat mengatasi keduanya. Yang paling dominan di antara pancaindera adalah indera penglihatan, yang menangkap warna sebagai tangkapan primer dan kemudian bentuk sebagai tangkapan sekunder.
-
Kedua, semua maujud yang menjadi objek ilmu terbagi dua jenis, yaitu maḥsūsāt (dunia empiri sensual), yakni semua objek indera penglihat, pendengar, perasa, pencium, dan peraba dan ma‘lūmāt (yang diketahui akal). Apa yang bukan objek pancaindera, yaitu semua mawjūd yang padanya tak terbayang sentuhan dan jarak, tak dapat diketahui dengan pancaindera, tapi hanya dengan argumen- arguman rasional, misalnya dengan menunjuk efek atau fenomena-fenomenanya, seperti daya-daya pancaindera sendiri, ilmu, kehendak, emosi-emosi, dan sebagainya.
-
Ketiga, pancaindera memiliki kelemahan dan kekurangan-kekurangan tertentu dibanding akal. Dalam al-Munqidz al-Ghazzālī membentang beberapa permisalan tentang lemahnya indera berbanding akal. Diantaranya adalah indera penglihat, sebagai indera terkuat, memiliki tujuh kekurangan.
-
mata tidak dapat melihat dirinya sendiri, sedangkan akal dapat menangkap yang lain, dirinya, dan sifat-sifat dirinya.
-
mata hanya dapat melihat sebagian yang ada, sebab ia tidak dapat menjangkau obyek-obyek akal dan obyek-obyek indera lain, seperti bau, rasa, suara, panas, dan sebagainya serta sifat-sifat psikis, seperti gembira, sedih, sakit, lezat, dan sebagainya; sedangkan bagi akal, semua yang ada merupakan lapangannya.
-
mata tidak dapat melihat sesuatu yang tak berkesudahan.
-
mata tidak dapat menangkap apa yang ada di balik tabir, sedangkan akal dapat beroperasi di ‘Arsy bahkan semua hakikat kecuali hakikat, zat dan perbuatan Allah.
-
mata tidak dapat melihat obyek sensual yang terlalu jauh atau terlalu dekat, sedangkan akal tidak dipengaruhi oleh jarak dan waktu.
-
mata tidak dapat melampai dunia warna dan bentuk, dan hanya dapat melihat obyek sensual pada lapisan luar dan mukanya saja, sedangkan akal mampu menembus bagian dalam dan esensi sesuatu.
-
mata sering menangkap sesuatu sesuai realitasnya. Misalnya ia melihat bintang-bintang dengan bentuk mata uang dinar yang bertaburan, sedangkan akal dapat membuktikan bahwa bintang dan matahari jauh lebih besar dari pada bumi.
Di dalam Mi‘yār al-‘Ilm, al-Ghazzālī menyatakan ketidaksepahamannya terhadap para pemikir yang berperinsip skeptisisme absolut, yang mengira bahwa tidak ada jalan bagi akal untuk mengetahui kebenaran. Pendapat ini tidak lain hanyalah kejahilan kaum sofis yang memiliki motif hendak membawa manusia ke arah dogmatisme.
Akal
Terma ‘akal’ (‘aql) berasal dari kata ‘aqala yang berarti sesuatu yang berbenteng kuat di puncak gunung dan tak terjangkau oleh tangan manusia karena kokoh dan kuatnya. Penamaan potensi ini dengan ‘akal’ menunjukkan potensial dan pentingnya peran akal bagi manusia. al-Ghazzālī merupakan figur yang pertama kali memasukkan logika peripatetik ke dalam kultur keilmuan Islam, dan bukan saja memandangnya sebagai muqaddimah ilmu, tapi juga sebagai salah satu syarat mujtahid, yang hukum mempelajarinya farḍ kifāyah bagi umat Islam.
Lebih jauh Sang Imām menjelaskan, bahwa akal itu ibarat cermin yang dapat menagkap objek sebagaimana realitasnya dan bersih dari kesalahan. Kalaupun pemikiran seseorang salah, maka kesalahan tersebut bukan terletak pada akal, tetapi dikarenakan seseorang dikuasai khayāl dan wahm. Untuk mengatasi hal ini, seseorang harus melakukan mujāhadah yakni, takhallī dan tajallī.
Al-Ghazzālī sangat yakin bahwa potensi akal cukup mampu untuk menangkap bukan saja yang terbatas, tetapi juga yang tak terbatas. Oleh sebab itu, objek akal adalah seluruh yang ada, dan semua esensi tidak terhalang bagi akal.
Al-Ghazzālī mengakui, bahwa di samping sering terjadi kesalahan dalam proses penalaran rasional, ilmu yang diperoleh akal melalui pancaindera, kadang juga mengalami distorsi pada tangkapannya. Yakni, apabila ada tangkapan luar yang menganggu akurasi indera, atau pada tahap bentukan khayāl dan wahm. Sebab khayāl dan wahm sering mangaburkan akal dalam menangkap objek metafisis dengan memaksakan kesan-kesan fisis-sensual seperti warna dan bentuk, serta bereksistensi dalam ruang dan waktu. Dengan demikian, untuk mencapai kebenaran ilmu-ilmu inferensial, diperlukan penalaran rasional yang benar. Khusus dalam masalah metafisis, akal harus jernih dari pengaruh khayāl dan wahm, serta dibutuhkan adanya petunjuk langsung dari Allah yang menyingkap esensi segala sesuatu sejelas mungkin.
Mengenai peran akal dan logika dalam mengenal Tuhan, al-Ghazzālī menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah, rasul, dan hari akhir secara global adalah bukan berdasarkan argumen tertentu, tapi oleh sebab-sebab yang komplek sepanjang proses pencarian kebenaran.
Meskipun al-Ghazzālī tidak menegaskan secara aksplisit apakah kewajiban pertama bagi mukallaf itu “mengenal Allah” atau penalaran yang menyampaikan pengenalan kepada Allah (ma‘rifatuLlāh). Namun, dalam al-Iqtiṣād ia menjelaskan bahwa penalaran rasional merupakan sebab mengetahui Allah, kenabian, dan kebenaran syara‘ yang alatnya adalah akal.
Imām al-Ghazzālī menyadari betul, bahwa rasionalisme ketika dihadapkan dengan sebagian persoalan metafisis, seperti mengetahui esensi zat, sifat, dan perbuatan Allah, maka prinsip-prinsip dan persyaratan logika tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya. Akal hanya mampu menganalogi yang ghaib kepada yang tampak, dan tidak mungkin memenuhi persyaratan logika. Dalam hal ini, al- Ghazzālī dengan jelas menolak metafisika spekulatif dari pada filosof yang menurutnya hanya takhmīn (terkaan-terkaan spekulatif) belaka, bukan sesuatu yang rasional, sehingga satu filosof dengan filosof lainpun sering terjadi kontradiksi.
Intuisi (dzawq)
Dalam al-Munqidz, Imām al-Ghazzālī menyamakan arti dzawq dengan wijdān.29 Namun lebih rinci lagi, dalam Misykāt ia menjelaskan bahwa dzawq memiliki potensi tersendiri berbanding daya-daya lain sebagai sumber ilmu yang terdapat pada manusia. Menurutnya, ada lima macam roh pada diri manusia yang semuanya merupakan cahaya untuk melihat objek, tetapi derajatnya berbeda, yaitu: rūḥ al-ḥisās, rūḥ al-khayāl, rūḥ al-‘aqlī, rūḥ al-fiqrī, dan rūḥ al-qudsī nabawī. Roh terakhir diartikan juga sebagai dzawq khāṣ nabawī (intuisi khusus kenabian) yang hanya dimiliki oleh para nabi dan wali, yang dengannya dunia metafisis yang transenden terlihat jelas.
Meskipun dikatakan bahwa ilmu yang diperoleh dengan ilham tidak diusahakan, tidak berarti bahwa tidak ada usaha manusia sama sekali untuk mencapainya. Tidak diusahakan di sini adalah dalam arti tidak diperoleh melalui perantara seperti melalui al-ḥawās atau relasi konsep-konsep. Untuk dapat memperoleh ilmu dengan jalan ilham, manusia harus berusaha membuat kondisi jiwa bersih secara menyeluruh selain dari Tuhan, dan memenuhi jiwa dengan mengingat Tuhan.
Secara garis besar, usaha ini digambarkan dalam dua tahap. Yang pertama adalah mengosongkan jiwa dari selain Tuhan dan yang kedua adalah mengisi jiwa dengan ingatan yang penuh kepada Tuhan. Usaha yang kedua ini berakhir dengan al-Fanā’ bi al-kulliyyāt fīLlāh atau lenyapnya kesadaran tentang segala sesuatu selain Allah.
Sesudah usaha ini berakhir, al-kasyf pun dengan sendirinya mulai terjadi, karena jiwa telah memiliki kesiapan untuk itu. Al-Ghazzālī menyebutkan kondisi kesiapan ini dengan kata ‘yaqẓah’.
Pada saat yaqẓah ini, seseorang dapat melihat para malaikat, arwah para nabi, mendengar suara mereka dan mengambil manfaat dari mereka. Selanjutnya, kemampuan meningkat kepada menangkap gambar- gambar dan pemisalan-pemisalan, bahkan sampai pada tingkat-tingkat yang sama sekali tidak dapat digambarkan dengan kata-kata.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia tetap harus berusaha untuk mencapai ilham atau kasyf itu. Di dalam al-Imlā’, al-Ghazzālī menyebut pula usaha untuk membuat kondisi jiwa mempunyai kesiapan menerima kasyf dengan istilah takhallī dan tajallī. Yang pertama adalah memilih menyendiri dan dan meninggalkan segala yang dapat mengalihkan perhatian dari Tuhan (al-Ḥaqq) dan yang kedua adalah mengikuti amalan para ṣādiqīn.
Di dalam al-Munqidz, al-Ghazzālī menilai dzawq (intuisi) sebagai sumber ilmu pengetahuan, lebih tinggi berbanding ‘aql al-mustafād. Kelihatannya, keinginan untuk memperoleh ilmu yang betul-betul diyakini itulah yang membuat al-Ghazzālī menggantikan ‘aql al-mustafād dengan dzawq. Dalam membandingkan pengetahuan para filosof dengan pengetahuan para wali, ia menyatakan bahwa pengetahuan para filosof diperoleh dari dunia nyata melalui pancaindera. Sedangkan pengetahuan para wali diperoleh secara langsung melalui alam malakūt. Ini menunjukkan bahwa akal dalam arti daya pikir yang digunakan filosof tidak mempunyai kemampuan untuk berhubungan dengan alam malakūt.
Dengan dzawq, sesuatu yang diperolehi tidak sekedar disadari, tetapi juga dirasakan kehadirannya bahkan juga dilihat (musyāhadah). Pengetahuan seperti ini jelas lebih meyakinkan bagi subjek yang mengetahui daripada pengetahuan yang diperoleh melalui pikiran. Dengan adanya dzawq, akal tidaklah hilang dari sarana pengetahuan. Kedudukan akal hanya dibatasi pada kegiatan menangkap pengetahuan dengan jalan berpikir terhadap apa yang diterima oleh indera dan objeknya dibatasi pada pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena.
Dalam perspektif al-Ghazzālī, qalbu manusia pada fitrahnya siap menerima semua esensi yang menjadi objek ilmu. Adapun ilmu yang dimaksud, diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni syar‘iyyah dan ghayr al-syar‘iyyah.
-
Ilmu-ilmu syar‘iyyah adalah ilmu yang diambil secara taqlīd dari nabi dengan mempelajari dan memahami al-qur’an dan hadits, dan tidak dapat diperoleh dengan akal semata.
-
Ilmu-ilmu ghayr al-syar‘iyyah adalah ilmu-ilmu yang diperoleh dengan akal, dalam arti bukan dengan taqlīd melainkan dengan proses belajar dan pembuktian-penyimpulan, guna merealisasikan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, dalam klasifikasi ini, kalām dan filsafat menurut al-Ghazzālī tidak masuk sebagai disiplin tersendiri. sebab, kalām tidak lain hanyalah suatu upaya yang bersifat polemik-apologetik dan tidak dapat mencapai kebenaran yang hakiki atau membuat orang menjadi beriman dengan sempurna.
Demikian pula al-Ghazzālī memandang filsafat bukan sebagai sebuah disiplin ilmu parsial, melainkan lebih merupakan aliran atau model pemikiran, yang disiplin-disiplin cabangnya sudah berdiri sendiri-sendiri. Seperti matematika dan fisika sudah otonom, manakala logika dan metafisika sudah ditransfer ke dalam kalam, dan sebagainya.
Dari sudut hukum mempelajarinya, ilmu-ilmu syar‘iyyah ada yang farḍ ‘ain dan ada yang farḍ kifāyah. Sedangkan di antara ilmu-ilmu yang bukan syar‘iyyah ada yang terpuji, tercela, dan mubah. Yang terpuji adalah semua ilmu yang diperlukan untuk kemaslahatan dunia. Ia terbagi lagi menjadi dua, yaitu :
-
Farḍ kifayāh, yaitu semua ilmu yang mutlak dibutuhkan untuk tegaknya kehidupan duniawi, seperti ilmu kedokteran, matematika, teknologi industeri, pertanian, politik, militer, jahit-menjahit, dan sebagainya.
-
Faḍīlah (keutamaan) , yaitu kajian filosofis tentang ilmu-ilmu tersebut yang tidak mutlak diperlukan, tetapi menambah kekuatan bagi kadar yang diperlukan sebagai basis.
Pada hakikatnya, menurut Sang Imām, seperti yang dibentangkan dalam Iḥyā, semua ilmu sebagai kebenaran objektif tidak ada yang tercela. Dikatakan tercela karena faktor lain, yakni merugikan orang lain, seperti sihir, maupun terhadap diri sendiri seperti astrologi. Sedangkan yang termasuk ilmu mubah hukum mempelajarinya adalah selain ilmu-ilmu terpuji dan tercela seperti tersebut di atas.
Referensi
- Syed Nawab, Some Moral and Relegious Teaching of al-Ghazzālī (Lahore: S.H.M. Ashraf).
- al-Ghazzālī, Misykāt al-Awār wa Miṣfāt al-Asrār, (Bayrūt: Mazra‘at Bināyat al-Īmān, 1986).
- Al-Bazdawī, Kitāb Uṣūl al-Dīn (al-Qāhirah: Dār Iḥyā’ kutub al-‘Arabiyyah, 1963).
- Ṣiddīq Ibn Ḥasan al-Qanūjī, Abjad al-‘Ulūm (Damsyiq: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978).
- Muhammad Yasir, Manusia Menurut al-Ghazali, (Jakarta: Srigunting, 2002)