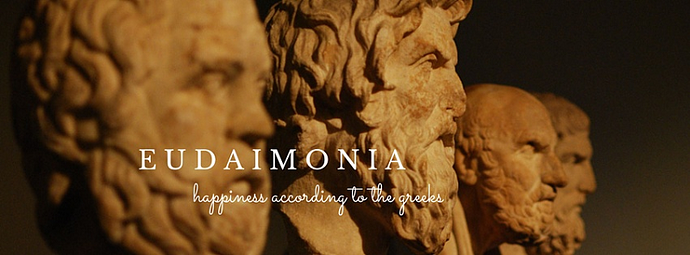Eudaimonic berasal dari bahasa Yunani daimon, yang berarti diri yang sebenarnya.
Kebahagiaan eudaimonic bermakna bahwa kebahagiaan adalah hasil dari perjuangan untuk mencapai aktualisasi diri, dimana dalam prosesnya akan sangat dipengaruhi oleh bakat, nilai, dan kebutuhan dari individu dalam menjalani hidup (Baumgardner, 2010).
Pandangan eudaimonic memiliki makna yang berbeda terkait eksistensi kebahagiaan, pandangan eudaimonic menyatakan kebahagiaan lebih bersifat objektif dan kesenangan yang subjektif tidak dapat disetarakan dengan kebahagiaan.
Kebahagiaan eudaimonic sifatnya benar-benar muncul dari dalam diri individu tersebut dan tidak terpengaruh dari kondisi eksternal individu tersebut. Kebahagiaan eudaimonic hanya akan didapatkan melalui aktifitas yang sejalan dengan tujuan hati yang sebenarnya.
Eudaimonia (kebahagiaan) dikenal melalui tulisan filsuf Aristoteles yang selanjutnya dalam ilmu psikologi menjadi istilah psychological well-being. Aristoteles (Ryff, 1989) menyatakan bahwa pengertian bahagia bukanlah diperoleh dengan jalan mengejar kenikmatan dan menghindari rasa sakit, atau terpenuhinya segala kebutuhan individu melainkan melalui tindakan nyata, individu mengaktualisasikan potensi-potensinya. Hal inilah yang merupakan tugas dan tanggung jawab manusia sehingga merekalah yang menentukan apakah menjadi individu yang merasa bahagia, merasakan apakah hidupnya bermutu, berhasil atau gagal.
Aristoteles berpendapat dalam ajaran etikanya, kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan bahwa usaha mencapai kebahagiaan, bila dipahami dengan tepat, akan menghasilkan perilaku baik. Ia mencari sesuatu yan gbaik baginya tetapi ada banyak macam aktivitas manusia yang terarah pada macam-macam tujuan tersebut dan menurut Aristoteles tujuan yang tertinggi ialah kebahagiaan (eudaimonia).
Ryff (1989) menjelaskan bahwa psychological well-being merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mendapatkan hal-hal di bawah ini, yaitu:
- menerima diri apa adanya (self-acceptance)
- menjalin hubungan hangat dengan orang lain (positive relation with others),
- mandiri (autonomy)
- mampu mengontrol lingkungan eksternal (environment mastery),
- memiliki tujuan hidup (purpose in life)
- mampu merealisasikan potensi diri secara continue (personal growth).
Tujuan tertinggi yang hendak dicapai manusia adalah kebahagiaan atau “eudaimonia” yang merupakan tujuan akhir kehidupan. Kata Aristoteles ”Kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang subjektif, abstrak atau ideal tetapi suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang termasuk keadaan bahagia (jiwa) itu terdapat pada manusia. Artinya bahwa tujuan yang dikejar adalah demi kepentingan diri sendiri, bukan demi kepentingan orang lain.
“Kebahagiaan itu nyata dialami (jiwa), tidak ideal, dan harus menjadi sesuatu yang praktis dialami dan dirasakan oleh (jiwa) manusia. Kebahagiaan ini harus ditemukan dalam pekerjaan dan kehidupan yang khas manusiawi".
Oleh karena itu kebahagiaan sejati terletak pada kehidupan yang aktif dari rasional atau dalam realisasi sempurna dan out working jiwa sejati dan dalam diri, secara terus-menerus berlanjut sepanjang hidup seseorang. Kebahagiaan harus didasarkan pada sifat manusia, dan dimulai dari fakta-fakta dari pengalaman pribadi. Isi dari setiap kebahagiaan ialah perbuatan sendiri yang bersifat khusus disempurnakan. Jadi kebahagiaan manusia terletak pada aktifitas yang khas manusiawi (dimiliknya) sebagai manusia yang terus-menerus disempurnakan.
Namun tujuan kehidupan; kebahagiaan tertinggi, yang dikejar oleh tiap manusia yang berpikir secara murni (melalui jiwanya), menurutnya manusia tak mungkin mencapainya sebab kebahagiaan yang tertinggi atau puncak kebahagiaan itu hanya dapat dicapai oleh para dewa.
Sebaliknya manusia hanya dapat mencoba mendekatinya dengan mengatur keinginan hatinya atau jiwanya (hasrat nous dan soulnya). Manusia hanya mengejar kebahagian di dunia ini (yang nyata), dan tak perlu mengejar kebahagiaan kekal, karena jiwa akan mati dan kebahagiaan kekal telah diambil oleh para dewa. Secara sinis mau dikatakan; untuk apa manusia mengejar kebahagiaan kekal versi Plato, jika kebahagiaan itu tidak tersedia (telah dicaplok para dewa).
Akhirnya Aristoteles menegaskan bahwa kebahagiaan manusia terdapat pada aktivitas yang khusus dan mengarah pada kesempurnaanya. Potensi khas manusia yang membedakan dari binatang atau makluk lain adalah berkat akal budi dan spiritualitasnya (jiwanya). Karena itu, aktivitas dan aktualitas manusia yang bisa mengarahkan pada kebahagiaan adalah semua bentuk aktivitas yang melibatkan bagian-bagian jiwa yang berakal budi.
Namun, karena manusia hidup dalam alam dunia dan masyarakat, maka aktualisasi dari akal budi dan jiwanya tersebut bukan semata-mata diarahkan pada yang maha budi dan idea, tetapi juga diarahkan pada kehidupan kongkrit melalui partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Tegasnya, kebahagiaan (jiwanya) tercapai dengan cara memaksimalkan potensi diri untuk memandang realitas rohani (spiritualitas-jiwa) di satu sisi, dan aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat di sisi yang lain.
Di sinilah Aristoteles membatasi ruang gerak jiwa dan tujuan kebahagiaan yang sempurna dalam realitas polis. Jadi, Aristoteles mengemukakan pandangan kontra versi sekaligus paradoks sehubungan dengan hakekat jiwa dan kebahagiaan jiwa yang bersifat rohani, yang digagaskan sebelumnya.
Akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
-
Tujuan akhir kehidupan adalah kebahagiaan sama dengan Plato dan Aristoteles, berhubungan dengan polis Yunani kuno (unsur kesamaan).
-
Letak perbedaan adalah Plato menekankan pada kebahagian abadi setelah kematian seseorang, sementara Aristoteles menekankan pada kebahagian kini dan sekarang di dunia ini (bukan di dunia kayangan; ideal Plato atau dunia nanti theolog).
-
Plato dan filsuf serta ilmuan pada umumnya termasuk theolog (agama-agama) mengakui bahwa jiwa adalah penyebab tubuh jasmani hidup dan jiwa itulah yang akan hidup terus (keabdian jiwa) setelah kematian tubuh.
Gagasan ini berbeda dengan Aristoteles sehubungan dengan gagasan fungsi jiwa dengan tubuh. Menurutnya jiwa akan mati dan hancur bersama tubuh, sedangkan akal budi dan roh (nous dan nus) tetap hidup. Inilah paham keabadian nous Aristoteles yang kontraversi.
Kebahagiaan dalam bahasa Yunani di kenal dengan istilah eudaimonia yang memiliki arti kebahagiaan. Kata ini terdiri dari dua suku kata “en” (“baik”, “bagus”) dan “daimon” (“roh, dewa, kekuatan batin”).
Kendati demikian, kata kebahagiaan dalam bahasa Indonesia tersebut masih belum cukup kokoh untuk menjelaskan maksud pengertian asli dari kata Yunani tersebut. Secara harafiah eudaimonia berarti “memiliki roh penjaga yang baik”. Bagi bangsa Yunani, eudaimonia berarti kesempurnaan, atau lebih tepat lagi, eudaimonia berarti “mempunyai daimon yang baik” dan yang dimaksudkan dengan daimon adalah jiwa.
Sementara itu, terdapat sebuah pandangan yang berakar dari istilah ini, yaitu Eudaimonisme. Eudaimonisme adalah pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan. sebagai tujuan segala tindak-tanduk manusia.
Dalam eudaimonisme, pencarian kebahagiaan menjadi prinsip yang paling dasariah. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya terbatas kepada perasaan subjektif seperti senang atau gembira sebagai aspek emosional, melainkan lebih mendalam dan objektif menyangkut pengembangan selurah aspek kemanusiaan suatu individu (aspek moral, sosial, emosional, rohani). Lihat K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani. (Jogjakarta:Kanisius, l999)
Aristoteles berpendapat dalam ajaran etikanya, kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan bahwa usaha mencapai kebahagiaan, bila dipahami dengan tepat, akan menghasilkan perilaku yang bajik. Dalam segala perbuatannya manusia mengejar suatu tujuan. Ia mencari sesuatu yang baik baginya tetapi ada bannyak macam aktivitas manusia yang terarah pada macam-macam tujuan tersebut. Dan menurut aristoteles tujuan yang tertinggi ialah kebahagiaan (eudaimonia).
Setiap manusia memiliki tujuan hidup. Menurut Aristoteles, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia). Orang yang sudah bahagia tidak memerlukan apa-apa lagi pada satu sisi, dan pada sisi lain tidak masuk akal jika ia masih ingin mencari sesuatu yang lain. Hidup manusia akan semakin bermutu manakala semakin dapat mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidup, manusia akan mencapai dirinya secara penuh, sehingga mencapai mutu yang terbuka bagi dirinya.